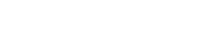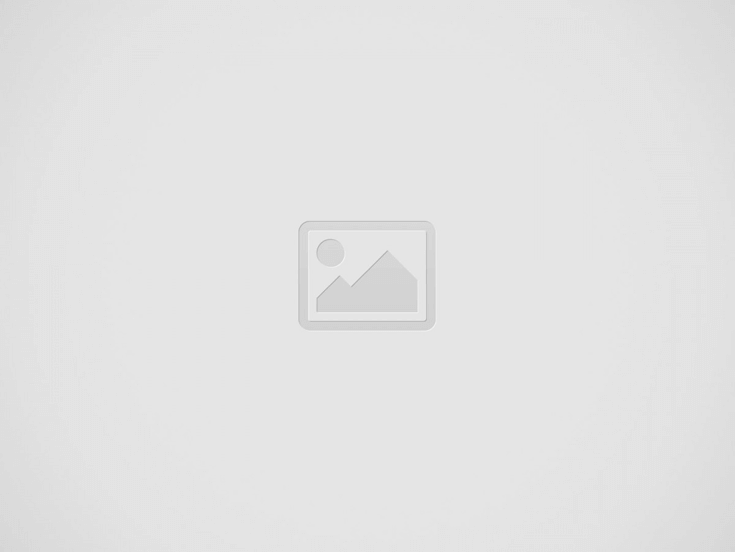Koran Sulindo – Pertengahan bulan Juni yang lalu di dunia maya tersebar berita Martin Aleida meraih penghargaan cerpen terbaik Kompas lewat tulisannya yang berjudul Tanah Air.
Martin memang seorang wartawan dan penulis profesional, sastrawan yang tumbuh besar dan berkarya di zaman Soekarno. Saya tidak tahu apakah di antara 20 kandidat itu, Martin satu-satunya yang punya latar belakang hubungan dengan Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra). Kalau jawabannya positif, maka tidak terlalu mengherankan kemenangannya dalam kompetisinya dengan penulis-penulis yang lahir dan besar di zaman Orde Baru.
Saya berkenalan dengan Martin Aleida pada 2014 di Jakarta. Saya diberi kumpulan cerpen yang baru saja keluar edisi ketiganya, Mati Baik-Baik, Kawan. Orang senang membaca cerpen-cerpennya. Asyik dan enak, kita dibawa menyusuri kehidupan dan pengalaman para pelaku ceritanya. Di samping keahliannya memilih dan merajut kata-kata, Martin menemukan pembantaian dan persekusi kejam rezim fasis Soeharto sebagai sumber inspirasi kaya dan luas yang tak akan pernah habis.
Di kulit belakang buku itu terdapat komentar Agung Ayu Ratih, peneliti sejarah dan sastra yang bermukim di Kanada. Ia menulis perasaan dan kesannya setelah membaca Melarung Bro di Nantalu, salah satu cerpen dengan Sobron Aidit sebagai tokohnya. Ratih mengungkapkan ia kenal dan pernah menginap di apartamen Sobron di Paris.
Kebetulan sekali saya termasuk orang yang juga kenal Sobron. Saya bahkan kenal istri dan kedua anak perempuannya. Saya kenal mereka tidak saja di Paris, tapi juga di Tiongkok, ketika anak-anaknya masih berumur kira-kira empat atau lima tahun.
Terus terang, perasaan dan kesan saya setelah baca Melarung Bro di Nantalu sangat lain bahkan bertentangan dengan yang dirasakan A.A. Ratih. Ratih dibikin menangis oleh perjalanan hidup Sobron yang “memilukan”. Sedangkan saya dibikin sangat kecewa dan marah “besar” atas kebohongan dan memutarbalikkan fakta tentang kehidupan Sobron dan orang-orang Indonesia lainnya di Tiongkok ketika itu. Kebohongan dan memutarbalikkan fakta itu berhubungan dengan sikap negatif terhadap Revolusi Besar Kebudayaan Proletar (RBKP).
Dalam diskusi tentang buku Trotskyisme?… Sosialisme di Satu Negeri atau Revolusi Permanen, pada Mei lalu di Jakarta, Martin Aleida berkomentar dan menyatakan pendapatnya atas buku tersebut bahwa ia tidak pernah percaya pada tulisan yang berasal dari sumber sekunder. Lantas bagaimana mereka yang ingin menulis dan menganalisa kejadian-kejadian sejarah yang para pelakunya sudah meninggal? Jika kita mengikuti logikanya Martin, maka semua buku sejarah di dunia ini tidak ada yang patut dipercayai karena informasinya berasal dari sumber sekunder. Tidak mungkin kita mewawancarai langsung, misalnya, Pangeran Diponegoro, atau Lenin, atau Trotsky, atau Napoleon!
Tapi anggaplah Martin benar. Sumber sekunder tak patut dipercayai. Bagaimana dengan sumber informasi yang ia gunakan untuk menulis Melarung Bro di Nantalu? Saya tidak tahu apakah Sobron menceritakan langsung kepada Martin perjalanan hidupnya selama di Tiongkok atau ia baca tulisan Sobron. Artinya apakah cerpennya itu berdasarkan pada sumber sekunder atau sumber primer? Anggaplah Martin bertolak dari sumber primer, karena ia tidak percaya pada sumber sekunder. Bagaimana kalau sumber primernya itu berisi kebohongan dan memutarbalikkan fakta, seperti yang terjadi pada Melarung Bro di Nantalu?
Saya kenal betul Sobron dan keluarganya, bahkan pernah tinggal dalam satu kompleks, hanya berlainan gedung. Sebenarnya kehidupan pribadi Sobron, dari segi psikologis, jauh lebih baik dibanding dengan kawan-kawan yang harus hidup di Tiongkok dengan meninggalkan istri dan anak di Indonesia dalam keadaan tak menentu, tanpa berita. Apa yang dimiliki dan dinikmati Sobron merupakan sebuah “kemewahan” yang sangat didambakan oleh puluhan kawan-kawan lain. Jadi melekatkan kata “memilukan” kepada “perjalanan hidup” Sobron, menurut saya, sama sekali tidak patut.
Pada halaman 158, paragraf pertama tertulis, “Revolusi Kebudayaan melanda Tiongkok. Bukan cuma kaum komunis yang dicap jadi borjuis di negeri itu saja yang jadi sasaran. Juga orang-orang Indonesia yang menjadi tamu perayaan hari jadi Republik Rakyat Tiongkok.” Lalu, pada paragraf kedua berbunyi: “Bro dan kawan-kawannya disingkirkan dari kota. Sama seperti kaum komunis lokal, yang dituduh terjangkit penyakit borjuis dan harus dicuci otaknya, Bro juga menemukan nasib yang tak kalah buruknya. Bersama kawan-kawannya, dia digiring ke pedesaan. Dia dipaksa melakukan kerja badan, bertani, sebagai hukuman untuk gaya hidup yang dicap berleha-leha ala tuan tanah. Bro, yang semasa kecil, di kota kami, ikut mengejek dan melempari apek, yaitu Tionghoa tua dan papa, yang sedang membuang kotoran manusia ke sungai, sekarang nyahok. Dia dipaksa mengangkut kotoran manusia untuk disiramkan ke tanaman sebagai pupuk, semacam pembenaran terhadap petuah Ketua Mao bahwa pabrik pupuk terbesar di dunia ada di perut manusia.”
Kebohongan
Kebohongan, memutarbalikkan fakta, fitnah dan ejekan terhadap rakyat Tiongkok dan Ketua Mao! Siapa yang mencap dan menjadikan orang-orang Indonesia sasaran Revolusi Kebudayaan? Siapa yang menyingkirkan dan menuduh orang-orang Indonesia terjangkit penyakit borjuis dan harus dicuci otaknya? Dari 120 orang Indonesia yang tinggal satu kompleks dengan saya, tak satupun yang pernah jadi sasaran RBKP! Kalau Sobron atau siapapun menyatakan orang-orang Indonesia dijadikan sasaran RBKP, maka mereka adalah pembohong besar! Adalah kenyataan , di samping makan, minum, tempat tinggal gratis, untuk menghadapi panas lebih dari 40 derajat celcius, orang bisa beli blok es untuk ditaruh di bawah tempat tidurnya. Itulah pendingin ruangan versi Tiongkok ketika itu yang merupakan barang mewah!
Untuk menghindari panas yang luar biasa itu, sebagian dari penghuni kompleks malah pernah memenuhi undangan tuan rumah untuk berlibur ke Tsingdao. Mereka tinggal di hotel, di tepi laut, dan makan enak di tengah-tengah berkobarnya RBKP! Kontradiksi internal di kalangan orang Indonesia sendiri yang membuat sebagian memilih tidak ikut ke Tsingdao. Dan juga kontradiksi internal yang membuat sebagian orang Indonesia menuduh pimpinan dan mereka yang tidak masuk dalam grupnya sebagai orang-orang revisionis dan menganggap grupnya sendiri Marxis-Leninis!
Apakah Sobron dan kawan-kawannya merasa “digiring” dan “dipaksa” ke pedesaan? Martin harus tahu bahwa mereka yang tidak mau pergi ke pedesaan, punya alternatif. Yaitu keluar meninggalkan Tiongkok! Saya termasuk orang yang memilih jalan itu, karena tidak ingin mengabadikan “titel” SMA saya. Kalau Sobron punya nyali dan betul-betul merasa “disiksa”, “dihukum”, “dipaksa bertani dan angkut tahi”, mengapa tidak pilih keluar Tiongkok?
Di samping itu, belajar kepada kaum tani melalui “turun ke bawah” (turba) dan “tiga sama” (sama bekerja, sama makan, sama tidur) adalah kebijakan yang diterapkan Lekra. Apa Martin sudah lupa? Mao juga mengajarkan rakyatnya untuk belajar kepada kaum tani. Makanya selama RBKP mahasiswa dan kaum intelektual didorong untuk pergi ke pedesaan, tinggal dan bekerja bersama kaum tani. Tapi, kaum imperialis dan antek-anteknya serta medianya melihatnya sebagai “hukuman” dan “siksaan” terhadap kaum intelektual. Tak ketinggalan orang-orang revisionis modern (remo) dan orang-orang Trotskyis yang memang pada dasarnya punya sikap meremehkan dan menghina kaum tani.
Kalimat “Akhirnya Bro berniat melarikan diri, dan dia menemukan jalan untuk menyingkir dari siksaan berkepanjangan” adalah isapan jempol Martin sendiri! Sobron meninggalkan Tiongkok dengan tiket dibayar pemerintah Tiongkok. Sebelum pergi, ia diajak ke toko “Persahabatan” untuk membeli semua yang diperlukan. Kemudian masih diberi bekal US$ 700 dolar. Itukah cara Bro “melarikan diri” dan “menyingkir dari siksaan berkepanjangan”?
“…Bro dan kawannya yang bertubuh kecil itu, menyeret-nyeret kaki, luntang lantung mencari jalan untuk bertahan hidup. Didorong angin musim panas, terkadang tubuh Bro yang gembur kelihatan sempoyongan seperti layang-layang yang putus tali teraju……..”. Lukisan patetis ini hanyalah fantasi! Bro sudah ditunggu oleh banyak kawan yang terlebih dulu tiba dan menetap di Paris. Bro tidak terdampar sendiri, menderita kelaparan atau kedinginan di Paris seperti Oscar Wilde, penulis dan penyair Inggris abad ke-19!
”Bro adalah sebuah perjalanan hidup yang tidak biasa, yang tiada tara.” Aduh, begitu dramatis dan penuh heroisme! Padahal kehidupan Bro biasa-biasa saja: makan, minum, tidur gratis, sama seperti ratusan orang-orang Indonesia lainnya. Bahkan jauh lebih baik, karena anak dan istri ada di sampingnya. Istri meninggal pun bukan karena “hukuman” atau “siksaan” atau tidak bisa bayar ongkos pengobatan, seperti buruh dan tani sekarang atas apa yang disebut sebagai “Sosialisme” dengan ciri Tiongkok. Orang-orang Indonesia mendapat perlakuan dan pengobatan istimewa dan yang terbaik. Saya menyaksikan dan mengalami sendiri perlakuan demikian.
Dalam cerpen Tanah Air, kembali Martin mencerminkan ideologi dan pandangan politik anti-RBKP, anti-sosialis dan anti-Mao. Saya sudah biasa menghadapi dan mendengar pendapat orang yang, setelah keluar Tiongkok dan hidup makmur di negeri-negeri welfare, membelejeti dirinya sebagai revisionis dan pendukung restorasi kapitalis Deng Xiao-ping. Bertahun-tahun saya membantah tulisan-tulisan revisionis, anti-RBKP, anti-sosialis dan anti-Mao dari almarhum Suar Suroso dan almarhum Ibrahim Isa. Bertahun-tahun saya melayani perdebatan dengan Chan CT. Ketiga-tiganya pernah tinggal lama di Tiongkok. Tidak heran kalau di antara mereka yang bersedia diwawancarai Martin terdapat pendukung restorasi kapitalisme.
Jadi bukan RBKP yang “mencap” dan menjadikan Bro dan kawan-kawannya itu “sasarannya”. Bukan RBKP yang “menuduh” mereka “terjangkit penyakit borjuis” dan harus “dicuci otaknya”. Setelah mereka keluar Tiongkok, mereka sendirilah yang membuka “kedok” yang selama di Tiongkok mereka pasang karena takut dikritik oleh kawan-kawan dan komunitas Indonesia sendiri. Hal mana menunjukkan sifat pengecut dan kemunafikannya. Untuk menutupi pengkhianatannya, mereka mengikuti jejak kaum revisionis pengambil jalan kapitalis Tiongkok pimpinan Deng Xiaoping yang terus menerus menyebarkan kebohongan dan fitnah terhadap RBKP dan Mao Tse-Tung.
Perlu dan penting diketahui bahwa sosialisme Tiongkok di bawah pimpinan Mao Tse-Tung tidak pernah mengkhianati rakyat dan orang-orang Indonesia yang tinggal di Tiongkok ketika itu. Justru selama RBKP berkobar, solidaritas rakyat Tiongkok terhadap perjuangan rakyat Indonesia yang ketika itu dibantai, dipenjara, disiksa dan dikejar-kejar rezim fasis Suharto semakin besar. Mao Tse-Tung mengajar rakyatnya untuk mengencangkan ikat pinggang lebih erat guna membantu perjuangan rakyat sedunia melawan imperialisme, neo-kolonialisme serta antek-anteknya.
Ketika klik revisionis Deng Xiao-ping pengambil jalan kapitalis berhasil melakukan kudeta dan menguasai partai dan pemerintah, berubahlah kebijakan Tiongkok terhadap orang-orang Indonesia. Mereka yang masih mau berpolitik harus meninggalkan Tiongkok. Kasarnya diusir! Tiongkok berkepentingan membuka kembali hubungan kenegaraan dengan rezim fasis Suharto. Dikhianati prinsip internasionalisme proletar, dan dijunjung sovinisme. Itulah kenyataan dalam “sosialisme” dengan ciri Tiongkok pada saat ini.
Mengapa sosialisme dalam tanda kutip? Karena kata “sosialisme” itu hanya penipuan belaka. Di Tiongkok, sejak berkuasanya klik revisionis Deng, setapak demi setapak dibongkar struktur ekonomi sosialis. Untuk membenarkan pengkhianatannya terhadap sosialisme, kaum revisionis sampai berani menyatakan bahwa penghisapan manusia atas manusia dibutuhkan untuk membangun sosialisme. Bayangkan! Bung Karno saja yang bukan komunis sangat anti exploitation de l’homme par l’homme. Sosialisme ala Indonesia yang beliau dambakan bukan sosialisme yang menghalalkan penghisapan manusia atas manusia lain. Namun orang remo tidak mengakui revisi yang dilakukannya pada prinsip-prinsip dasar sosialisme. Mereka menolak disebut remo. Orang yang menolak revisi itu malah dicap “dogmatis”! Kalau dalam sosialisme dibenarkan penghisapan, lantas apa bedanya dengan kapitalisme?
Usul saya kepada Martin, pelajari sendiri apa sebenarnya hakikat dari RBKP. Jangan hanya menelan bulat-bulat propaganda imperialis anti-Mao dan anti-komunis seperti mereka yang masih “mengunyah-ngunyah” propaganda Orde Baru tentang peristiwa 1965. [Tatiana Lukman]