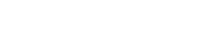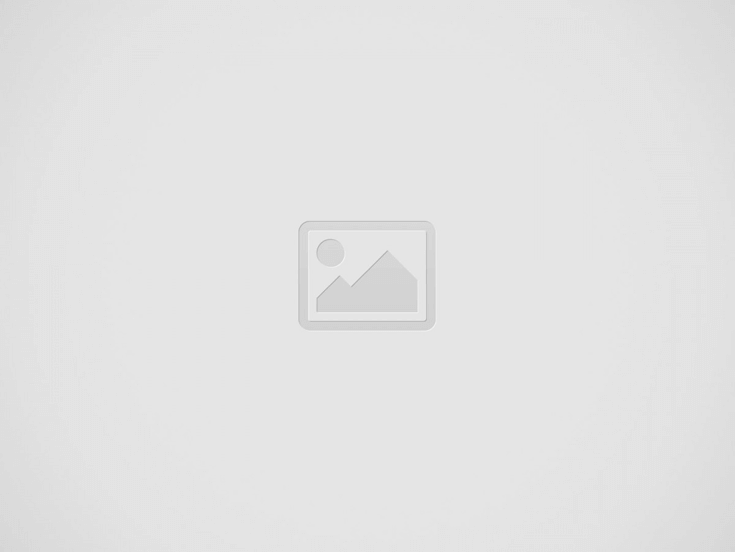DALAM kebudayaan masyarakat Jawa, ada yang disebut tradisi gowok dan ada pula tradisi ronggeng.
Konon tradisi gowok berasal dari Tiongkok yang sampai di tanah Jawa. Dan tradisi ini bisa dibilang tradisi untuk mengajari remaja laki-laki bisa menjadi seorang pria dewasa. Tradisi ini pernah atau masih dapat ditemui di Purworejo, Blora, dan Banyumas.
Sedangkan pertunjukan Ronggeng ketika pada zaman penjajahan Belanda, dihadirkan untuk menghibur para tukang kebun dan tentara. Di masa itu, sosok ronggeng menjadi primadona dan pelipur lara yang paling digandrungi.
Menjadi menarik, karena tradisi ini lebih mengacu pada budaya tubuh untuk mendapatkan identitas tertentu yang ada dalam nilai-nilai budaya yang terkait..
Gowok
Gowok sendiri adalah sebutan untuk perempuan dalam kebudayaan Jawa yang disewa untuk mengajarkan perihal rumah tangga dan seksualitas kepada laki-laki berusia remaja atau sebelum menikah
Keluarga mempelai laki-laki yang menyewakan gowok untuk anak mereka sebelum menikah. Gowok akan mengajarkan salah satunya tentang memuaskan istri dan memperkenalkan tubuh perempuan. Calon mempelai laki-laki akan tinggal di rumah gowok selama beberapa hari untuk kemudian menerapkan ilmu yang sudah diperoleh kepada istrinya ketika sudah menikah. Setelah pelatihan berlangsung, gowok akan melaporkan kemampuan calon mempelai pria kepada orang tuanya. Gowok biasanya adalah perempuan dewasa berumur 20-40-an tahun.
Tradisi ini konon dibawa oleh Goo Wook Niang, sosok wanita Tiongkok yang membawa tradisi tersebut ke Jawa. Karena lidah orang Jawa saat itu agak sulit melafalkan nama lengkap Goo Wook, maka disingkat jadi ‘gowok’ saja.
Biasanya remaja laki-laki bisa menghabiskan waktu selama beberapa lama dalam “asuhan gowok”. Masa ini disebut nyantrik. Bisa berlangsung selama beberapa hari, bisa juga seminggu. Sang remaja akan diajari bagaimana menjadi lelananging jagad yang sejati. Bukan hanya soal urusan ranjang saja yang diajarkan oleh seorang gowok. Gowok pun akan mengajari berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga dan bagaimana cara memperlakukan istri dengan baik.
Ada sederetan penulis yang mengangkat cerita tentang gowok ini, salah satu penulis pertama nya adalah Liem Khing Hoo (1905-1945). Konon di akhir hayatnya Liem Khing Hoo tinggal di pegunungan Tengger sembari melawan penyakit parunya. Penulis keturunan Tionghoa Indonesia yang mempunyai nama pena Romano ini menulis novel-novel etnografis, yang sayangnya kini tak lagi banyak diingat.
Sederet karyanya seperti Kembang Widjajakoesoema (1830), Edjoin (1932), Dewi Poeti (1932), Brangti (1934), Gowok (1936), Merah (1937) dan Tengger (1940) ditulis dengan bahasa Melayu-rendah atau Melajoe-adoekan, di mana kata peneliti kawakan asal Prancis Claudine Salmon memumpunkan perhatian pada kehidupan pedusunan, tradisi suku terasing serta dunia priyayi (lihat Sastra Indonesia Awal: Kontribusi Orang Tionghoa. 2010, h. 375-397).
Salah satu karya Romano, Gowok, terbit pertama kali pada Maret 1936 di Tjerita Roman edisi VII No.87. Novel ini mengangkat kisah bertema couleur locale adat turun temurun gowokan di dusun Soediredja, Banyumas Wetan.
Ronggeng
Ronggeng sendiri adalah figur utama kebudayaan Banyumas yang tak lepas dari ironi. Konon, menurut ingatan kolektif masyarakat Banyumas, ronggeng lahir sebagai seni rakyat agraris bagian dari ritus kesuburan.
Pada abad ke-17, kehidupan agraris di Banyumas penuh risiko, pajak dan pemerasan sewenang-wenang telah berakibat kosongnya sebagian besar desa yang berada di sepanjang lembah subur sungai Serayu. Dalam situasi itu, ketika banyak penduduk meninggalkan Banyumas, ronggeng menjadi satu-satunya figur budaya yang tetap bertahan.
Berdasarkan catatan Kapten Godfrey Baker dalam Memoir of a survey of the prince’s dominions of Java yang terbit pada 1816 (baca Peter Carey dalam Kuasa Ramalan Pangeran Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama di Jawa, 1785-1855 Jilid I. 2011), pada titi mangsa 1815, ronggeng menjadi pemuas kesenangan bagi perpanjangan tangan keraton Surakarta yakni Raden Tumenggung Yudonegoro. Para elite keraton Jawa Tengah Selatan sendiri, sebagaimana ungkapan di kalangan Indo-Belanda di kota kerajaan pada 1930-an, memang kerap digambarkan memiliki kesenangan pada ‘anggur dan perempuan’ (baca Peter Carey dan Vincent Houben dalam Perempuan-perempuan Perkasa di Jawa Abad XVIII-XIX. 2016.h.23)
Posisi ronggeng sebagai penghibur dan menjamu tamu-tamu kerajaan di masa kejayaan kerajaan-kerajaan Jawa juga disebut dalam penelitian Sunaryadi berjudul Lengger Tradisi & Transformasi (ISI Yogyakarta, 2000). Sunaryadi menyebutkan bahwa ronggeng sebagai penghibur telah digambarkan dalam Serat Centhini Jilid 8, pupuh 456, bait 5-9.
Disinyalir kedua tradisi ini sekarang masih tetap ada dan masih dijalankan, walaupun hanya dalam skala kecil dan hanya didaerah tertentu.
Tidak ada keterhubungan langsung antara gowok dan ronggeng sebenarnya, hanya sekedar menyarikan sepotong kisah dari masa lalu yang memiliki satu keterkaitan yaitu berlakunya fenomena budaya tubuh untuk mencapai identitas dalam nilai budaya tertentu. [S21]