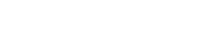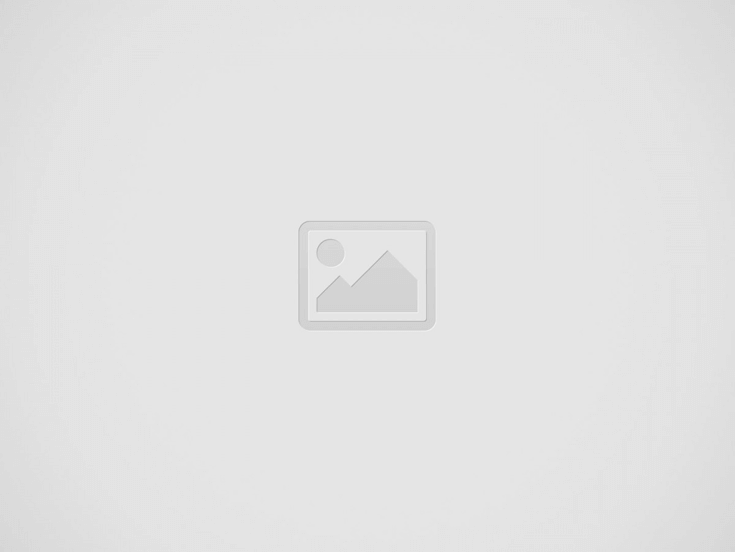Koran Sulindo – Keterbukaan politik di Indonesia setelah era reformasi yang ditandai oleh mundurnya Suharto ternyata berlangsung cepat dan gaduh. Dengan satu gejala dominan yaitu makin hilangnya toleransi. Itulah gambaran umum yang ada pada kalangan masyarakat Jerman yang tertarik mengikuti perkembangan politik di Indonesia.
Perkembangan politik dan budaya di Indonesia terkini itu menjadi fokus utama acara “Indonesien Tag” (Hari Indonesia) di Universitas Passau, Jerman. Penyelenggaranya Institut Studi Perbandingan Kawasan Asia Tenggara bekerjasama dengan Amnesty International.
Represi terhadap kelompok-kelompok minoritas, terutama dalam kaitannya dengan sistem keyakinan dan kepercayaan makin meningkat. Yang paling menonjol adalah aksi pembakaran dan pembunuhan terhadap rumah ibadah dan warga Ahmadiyah.
Apakah pluralisme di Indonesia, yang terangkum dalam motto Bhinneka Tunggal Ika sedang terancam?
Diskusi tentang pluralisme di Indonesia menghadirkan seorang Indonesianis kawakan Jerman, Profesor Bernhard Dahm, yang pernah meneliti soal identitas dan budaya di Indonesia selama era Soekarno dan pergantian ke Orde Baru di bawah Suharto, ditandai dengan pembantaian anti komunis 1965-1966.
Selain itu, hadir juga peneliti konflik Dr. Gunnar Stange, aktivis budaya Arahmaiani Feisal dan peneliti Asia Tenggara Dr. Kristina Grosmann.
Profesor Bernard Dahm mengingatkan kembali dimensi geografis dan sosiologis Indonesia, yang terdiri dari lebih 17 ribu pulau, dengan ratusan bahasa daerah yang masih digunakan secara aktif, serta beragam tradisi adat dan budaya.
“Sekalipun demikian, dalam sejarah Indonesia yang kita tahu, selama seribu tahun ini, hampir tidak ada konflik antar etnis dan budaya yang serius,” kata Dahm. Memang ada rivalitas dan ketegangan, tapi secara keseluruhan, bangsa-bangsa di Nusantara selalu berusaha mencapai kesepakatan melalui komunikasi dan dialog.
Hasrat besar untuk hidup bersama dengan rukun, mencapai puncaknya dalam pembentukan negara Republik Indonesia, ketika kelompok-kelompok nasionalis, agama maupun para pemikir sosialis berembuk untuk berjuang menuntut kemerdekaan dari penjajahan Belanda.
Bagi Dahm, hasrat hidup rukun dan perasaan saling memiliki ini dengan sangat gamblang tercermin pada sosok presiden pertama Indonesia, Ir. Soekarno. Sejak muda, Soekarno sadar bahwa ada tiga dorongan utama yang akan menentukan arah pembentukan bangsa dan Republik Indonesia: nasionalisme, agama, dan sosialisme, yang ketika itu dengan lantang disuarakan oleh gerakan komunisme.
Karena itu, Soekarno berusaha menjembatani pertentangan doktrin yang meruncing antara kelompok agama dengan kelompok komunis. Bagaimana mewujudkan cita-cita itu? Caranya, setiap kelompok harus siap “mengorbankan” doktrin mereka yang tidak bisa diterima pihak lain, lalu siap bekerjasama dengan konsensus yang dicapai demi pembangunan bangsa dan negara, sesuai motto Bhinneka Tunggal Ika.
Sayangnya, upaya Soekarno dengan pencanangan Nasakom gagal ditengah meruncingnya pertentangan ideologi dunia antara blok Barat dan blok Timur.
Peristiwa 1965 melempar perkembangan politik pluralisme di Indonesia jauh ke belakang. Sekalipun begitu, Dahm tetap merasa yakin, prinsip pluralisme adalah jalan satu-satunya bagi Indonesia untuk membangun masa depan yang baik.
“Semua kegaduhan yang kita lihat sekarang, ini hanya perkembangan di masa transisi. Indonesia akan kembali ke prinsip pluralisme, karena itu memang falsafah dasar bangds-bangsa yang hidup di sana”, kata Dahm.
Soekarno sangat yakin hal itu, juga setelah dia sudah diturunkan dari kekuasaan. “Dan saya juga yakin itu, jadi saya masih optimis”, kata Dahm yang masih bertemu dan berbicara dengan Soekarno setelah peristiwa 1965-1966.
Negara Gagal
Tapi tidak semua melihat Indonesia dengan optimistis. Peneliti Asia Tenggara Dr. Gunnar Stange dari Universitas Frankfurt bahkan menyebut Indonesia sebagai ‘negara gagal’ (failed state) dalam kaitannya dengan penegakan hukum.
Negara dan aparat Indonesia gagal memberi jaminan hukum terutama kepada kelompok-kelompok minoritas, sehingga yang bermunculan adalah kelompok-kelompok preman, yang akhirnya bertindak seperti penegak hukum dan memaksakan aturannya sendiri.
“Inilah kelompok yang disebut ‘vigilantes’, yang muncul dengan klaim sebagai pembela atau pelindung, ketika aparat penegak hukum tidak ada atau tidak memenuhi fungsinya”, kata Stange.
Dr Kristina Grosmann mengajak orang mengidentifikasi masalah pluralisme lebih cermat lagi. “Waktu saya di Indonesia, dalam hidup sehari-hari, di pedesaan, saya tidak lihat ada masalah dengan toleransi dan pluralisme. Di sana juga tidak ada masalah etnisitas.”
Tapi dalam kehidupan politik dan dalam perebutan ruang publik, identitas dan etnisitas memang tiba-tiba bisa menjadi persoalan.
“Jadi harus dibedakan, ada kehidupan nyata sehari-hari, dan ada tataran politisasi etnisitas dan identitas,” kata Grosmann. Di ruang publik, memang sekarang sedang terjadi perebutan klaim dan pertentangan. Hal itu biasa terjadi pada masyarakat yang sedang mengalami masa perubahan dan dipenuhi ketidakpastian.
“Yang jelas, untuk hidup dalam keberagaman, orang memang harus belajar. itu bukan hal yang diturunkan lewat kelahiran,” kata Grosmann.
Acara Indonesien Tag di Universitas Passau diramaikan dengan musik gamelan yang dimainkan mahasiswa-mahasiswa Jerman dibawah panduan Dr. Andras Varsanyi. Juga presentasi tentang program beasiswa dari mahasiswa Jerman yang dikirim ke Indonesia. Dan tentu saja ada sajian makanan dan penganan “gaya Indonesia” yang disiapkan para mahasiswa jurusan Kajian Kawasan Asia Tenggara. [dw.com/DS]