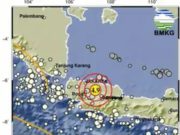INDONESIA dan gempa tampaknya kian hari kian tak terbantahkan keterkaitannya. Secara teori sudah lama kita ketahui bahwa hampir seluruh wilayah di negeri ini sangat berpotensi terkena gempa bumi. Karena posisinya yang berada di pertemuan tiga lempeng utama dunia, Eurasia, Indo Australia dan Pasifik atau populer dengan sebutan Jalur Cincin Api Pasifik. Kondisi geografis ini menjadikan Indonesia masuk wilayah rawan bencana gempa bumi.
Namun sadarkah kita bahwa sebenarnya sejak ratusan tahun lalu leluhur bangsa ini ternyata sudah fasih menyiasati gempa yang seringkali terjadi untuk mengamankan rumah mereka.
Suku Besemah, yang diperkirakan telah mendiami daerah Pagar Alam, di Sumatera Selatan sejak abad 6 Masehi, ternyata masih menjaga peninggalan nenek moyang mereka hingga kini, yaitu Rumah Tradisional Besemah atau Ghumah Baghi. Rumah tradisional dengan konstruksi yang sederhana ini mampu bertahan terhadap gempa yang sering terjadi akibat aktivitas vulkanik Gunung Dempo. Bahkan terbukti Rumah Besemah ini mampu bertahan hingga ratusan tahun.
Rumah kayu memang cenderung memiliki bahan bangunan yang ringan, namun bila tidak memperhatikan prinsip bisa-bisa terjadi kesalahan konstruksi. Terutama dalam hal pemilihan bahan bangunan. Yang banyak terjadi adalah menggunakan atap genteng dan kayu-kayu berat pada kuda-kuda atap, maka saat terjadi gempa struktur bagian bawah akan mengalami kerusakan karena struktur atas yang terlalu berat.
Namun hal ini tidak terjadi pada Rumah Tradisional Besemah karena berdasarkan data, bahan konstruksi Rumah Besemah yang paling berat ada di struktur bagian bawah sementara yang paling ringan ada pada struktur bagian atas. Kondisi ini lah yang membuat Rumah Besemah memiliki keseimbangan yang baik dalam mengalirkan gaya atau beban yang ada pada bangunan. Keseimbangan ini memang harus diperhitungkan karena akan mengurangi resiko kerusakan saat gempa terjadi.
Harus dipahami bahwa yang berbahaya dari gempa bukanlah peristiwanya, tetapi justru robohnya bangunan akibat gempa.
Contoh lain yaitu Rumah Aceh yang struktur bangunannya dari kayu saling dikaitkan satu sama lain. Dikunci dengan baji atau pasak sehingga lebih dinamis dan tahan guncangan gempa. Bila habis terjadi gempa besar, maka masyarakat Aceh akan memeriksa baji atau pasak yang ada pada rumah masing-masing. Bila terlihat menonjol keluar, segera dikembalikan ke posisinya semula dengan di pukul.
Jelas bahwa rumah yang bahannya berasal dari kayu atau bambu cenderung bertahan karena kayu dan bambu memiliki kelenturan terhadap guncangan gempa. Kearifan lokal itu ternyata sudah diadopsi juga oleh sejumlah negara seperti Jepang.
Secara umum konstruksi bangunan adat berupa rumah panggung juga mampu menahan guncangan saat gempa bumi terjadi. Seperti halnya rumah tradisional Sunda/Jawa Barat, struktur bangunannya memang menggunakan bambu dengan sistem ikatan antar komponen bangunannya serta lantai panggung yang tingginya sekitar 60 centimeter. Dengan sistem struktur seperti ini, bila terjadi guncangan gempa, bangunan hanya bergoyang dan tidak mengalami kerusakan. Lantai panggung setinggi 60 centimeter dimaksudkan untuk menjaga bangunan tetap utuh mesti jatuh ke permukaan tanah bila terjadi tanah longsor.
Salah satu contoh peristiwa gempa besar yang terjadi adalah di Minahasa pada 1845 yang mengakibatkan ribuan rumah rusak. Setelah peristiwa itu masyarakat Minahasa mulai membangun rumah dengan rancangan yang meminimalisir kerusakan jika terjadi bencana serupa. Sejak peristiwa tersebut maka rumah-rumah penduduk dibangun dengan ukuran kecil, tiang-tiangnya dipendekkan dan diperkecil serta rangka-rangka rumah dibuat sedemikian rupa agar tidak mudah roboh
Periode sebelum tahun 1845, menurut catatan Marwati dalam “Studi Rumah Panggung Tahan Gempa Woloan di Minahasa Manado” (Jurnal Teknosains, Vol. 8 No. 1, Januari 2014) adalah saat rumah-rumah orang Minahasa memiliki tiang-tiang penyangga yang cukup tinggi, yaitu antara 3-5 meter. Setelah gempa, rumah tradisional Minahasa tidak mengalami banyak perubahan, kecuali panjang tiang-tiang penyangganya yang dikurangi menjadi 1,5 sampai 2,5 meter dan diameter tiang-tiang tersebut menjadi lebih kecil yakni sekitar 30 centimeter.
“Rumah panggung Woloan di Minahasa merupakan rumah panggung tahan gempa pada semua struktur pondasi, dinding dan balok rangka utama dari kayu besi memenuhi syarat sebagai konstruksi gempa. Setiap balok saling kait mengait. Dinding dari papan maka tidak mudah retak atau pecah,” tulisnya.
Pengurangan tinggi tiang penyangga rumah dimaksudkan untuk memaksimalkan fungsi suspensi sehingga rumah tidak mudah roboh ketika ada getaran hebat. Fenomena tersebut dapat dibandingkan dengan kondisi rumah di sejumlah kampung tradisional di Jawa Barat yang jarak antara tanah dengan lantai rumah sangat pendek. Hal ini, selain karena masyarakat Sunda tidak memiliki budaya memanfaatkan kolong rumah sebagai tempat menyimpan cadangan logistik, juga dikaitkan dengan gempa bumi untuk mengantisipasi guncangan.
Rumah tahan gempa berdasarkan kearifan lokal memang mengutamakan konstruksi yang lebih fleksibel. Contoh lain adalah rumah joglo. Ada beberapa alasan mengapa rumah joglo lebih tahan terhadap gempa. Pertama, rangka utama (core frame) yang terdiri dari umpak, soko guru, dan tumpang sari, dapat menahan beban lateral yang bergerak horizontal ketika terjadi gempa. Kedua, struktur rumah joglo yang berbahan kayu menghasilkan kemampuan meredam getaran/guncangan yang efektif, lebih fleksibel, juga stabil. Struktur dari kayu inilah yang berfungsi meredam efek getaran/guncangan dari gempa. Ketiga, kolom rumah yang memiliki tumpuan sendi dan rol, sambungan kayu yang memakai sistem sambungan lidah alur dan konfigurasi kolom anak (soko-soko emper) terhadap kolom-kolom induk (soko-soko guru) merupakan unsur-unsur fleksibilitas dari rumah joglo terhadap gempa.
Sebagai rumah tradisional, Rumah Gadang tak perlu diragukan lagi untuk urusan kekuatan dan kekokohannya. Sudah terbukti kuat menahan gempa berkekuatan 7,6 SR (Skala Richter; satuan ukuran kekuatan gempa) yang sempat mengguncang Padang pada 2009 silam. Konstruksinya yang lentur dan solid bahkan mampu menahan gempa berkekuatan 8 SR. Kuncinya terletak pada rangka kayu yang berbentuk seperti perahu. Tiang bangunan bagian bawah juga dialas dengan batu agar bisa menahan getaran.
Atau contoh lain, tentu kita masih ingat gempa berkekuatan 7,8 SR yang mengguncang Nias tahun 2010. Waktu itu puluhan orang terluka dan ratusan rumah lebih luluh lantak karena gempa. Namun tidak dengan Omo Hada atau rumah tradisional Nias yang memiliki bentuk rumah panggung dengan ukuran besar memanjang ke belakang seperti sebuah kapal, yang terbukti kokoh menahan gempa. Konstruksinya didominasi kayu dan ‘cuma’ disatukan oleh pasak. Rahasianya terletak pada kayunya. Omo Hada tersusun dari kayu-kayu pilihan yang memiliki elastisitas tinggi. Sehingga ketika ada gempa, kayu penyangganya tak sampai roboh. Paling-paling cuma bergeser sedikit.
Rumah-rumah tradisional di Bali pun, terutama di bagian utara memiliki model konstruksi yang tidak menancap ke dalam tanah. Karena berada di atas permukaan, begitu ada pergerakan tanah dari bawah maka bangunan akan bergeser mengikuti dan tidak hancur berantakan. Bukti nyata adalah ketika terjadi gempa di Seririt, Buleleng pada tahun 1976. Rumah-rumah adat di Desa Sidatapa, Bali tetap bisa berdiri kokoh menghadapi gempa tersebut.
Sebetulnya kehidupan masyarakat sejak dahulu sudah sangat menyatu dengan alam, sehingga perilaku alam selalu menjadi perhatian utama mereka. Gempa menjadi salah satu pemicu manusia untuk membuat rumah yang aman dan nyaman. Rumah pun kemudian dibangun dengan pengetahuan teknologi turun-temurun yang terus disempurnakan. Kearifan nenek moyang kita memang tak sepantasnya ditinggalkan demi kenyamanan modern semata, karena pengetahuan akan adat maupun tradisi yang sudah dimiliki terbukti bukan sekedar jauh lebih tua namun juga bijak. Mungkin memang sudah saatnya kita kembali kepada kearifan lokal agar hidup lebih aman dan nyaman. [S21]