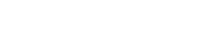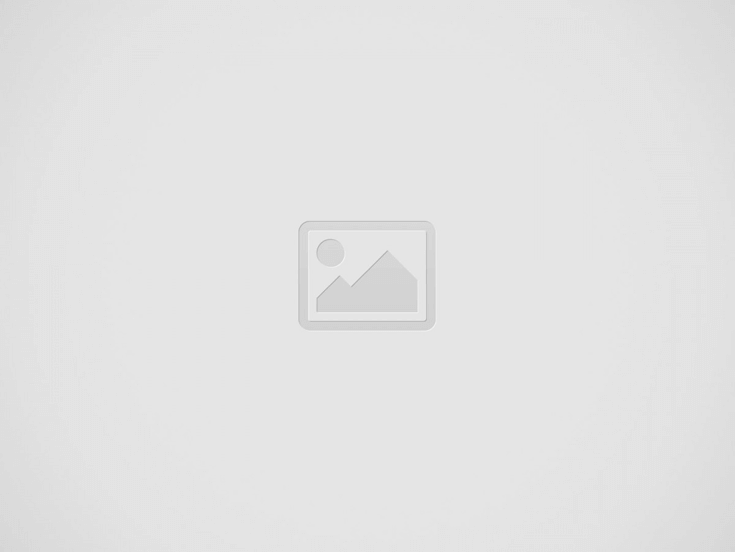Koran Sulindo – Namanya Muriel Stuart Walker. Lahir di Skotlandia, namun warga negara Amerika Serikat. Ia kemudian pindah dan menetap di Bali dan menggunakan nama K’tut Tantri. Pada masa Revolusi Kemerdekaan, pers Australia dan Singapura menjuluki dia sebagai Surabaya Sue. Karena, dia ikut berjuangan dengan rakyat Surabaya pada Pertempuran 10 November 1945. Itu sebabnya, Presiden Soekarno pernah memberi amanah kepada K’Tut Tantri untuk menulis pidatonya dalam bahasa Inggris.
Suatu hari, Bung Karno mengundang Tantri ke Istana Merdeka. Datanglah Tantri ke istana dengan mengenakan kebaya. Dan, Tantri pun kaget melihat penampilan Bung Karno yang mengenakan sarung, berjas lengan pendek, dan berkopiah.
Rupanya, Bung Karno mengganti pakaian seragamnya begitu melihat Tantri mengenakan kebaya. “Anda sudah repot-repot berdandan dengan busana nasional. Jadi, kurasa sepatutnya Anda kuterima dengan pakaian nasional pula,” demikian kata Bung Karno. Jadi, boleh dikatakan, Bung Karno ketika itu secara tidak resmi menyatakan kebaya adalah pakaian nasional perempuan Indonesia.
Kebaya memang sudah dikenakan perempuan Nusantara sejak berabad-abad lalu. Setidaknya, ketika bangsa Portugis datang ke Nusantara pada abad ke-16 dan melakukan ekspedisi dari Melaka menuju Madura, Bali, Lombok, Aru, dan Banda di bawah komando Antonio de Abreu, mereka sudah mencatat nama kebaya sebagai busana yang dikenakan banyak perempuan di negeri ini.
Pada 29 September 2013, situs thehindu.com menurunkan artikel tentang masyarakat Pulau Mulavukad (atau dalam bahasa lokal di sebut sebagai Pulau Bolghatty) di selatan India yang memiliki tradisi mengenakan kebaya atau kevaya dalam bahasa Kerala. Pulau Mulavukad memang berada di wilayah Kerala, yang pernah dijajah Protugis pada abad ke-16. Kebaya atau kevaya diperkenalkan bangsa Portugis ke masyarakat Pulau Mulavukad. Patut diduga, bangsa Portugis terkesan dengan kebaya, yang mungkin dirasa cocok dikenakan untuk negeri beriklim tropis.
Kendati demikian, tak diketahui secara pasti, kapan sebenarnya perempuan Nusantara mulai mengenakan kebaya sebagai busana. Sejarawan dari Prancis, Denys Lombard, dalam buku Nusa Jawa: Silang Budaya (1996) mengatakan, kebaya berasal dari kata dalam bahasa Arab, kaba, yang berarti ‘pakaian’.
Sejauh ini, apa yang diungkapkan Lombard itu boleh jadi benar. Karena, dalam budaya masyarakat Arab ada juga model pakaian perempuan yang dikenal sebagai abaya, semacam tunik panjang.
Namun, ada juga yang mengatakan, kebaya sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit, kerajaan besar di Jawa Timur, yang berdiri pada abad ke-13, tepatnya 1292. Ini juga kemungkinan benar, karena agama Islam yang kitab sucinya menggunakan bahasa Arab sudah masuk di Tanah Jawa pada abad tersebut dan semakin luas pengaruhnya menjelang runtuhnya Kerajaan Majapahit pada awal abad ke-16.DAALAM diskusi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, pada 22 Juni 2017 lalu, arkeolog dari Universitas Indonesia, Hasan Djafar, mengatakan artifak bercorak Islam dari masa Majapahit memang banyak ditemukan. Misalnya di Makam Troloyo, ada 100-an nisan dengan hiasan tulisan Arab. Nisan itu berasal dari masa 1203-1533 Masehi. Itu artinya ada sejumlah nisan yang berasal dari masa sebelum berdirinya Majapahit.
Namun, Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha, walau ditemukan juga koin bertulisan Arab dan nisan berkalimat syahadat di situsnya. “Majapahit tetap bercorak Hindu-Buddha, tecermin dalam peraturan perundang-undangan dan sistem teologinya,” ungkapnya.
Hal yang sama juga diungkapkan rekan sejawat Hasan Djafar, Prof. Dr. Agus Aris Munandar, yang menulis buku Catuspatha: Arkeologi Majapahit. Menurut Agus, Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha, yang bisa dilihat dari prasasti dan sistem pemerintahannya. Gelar raja, misalnya, sudah bisa menjadi bukti bahwa Majapahit merupakan kerajaan bercorak Hindu-Buddha. “Raden Wijaya bergelar Krtarajasa Djayawarddhana Anantawikramotunggadewa. Djayawardhana itu sudah jelas Hindu karena artinya ‘keturunan Dewa Wisnu yang bertakhta’,” tutur Agus.
Dari prasasti-prasasti yang dibuat pada abad ke-9 dan ke-10 dapat diketahui masyarakat Jawa pada masa itu memang sudah mengenal bermacam jenis tekstil. Ada ratusan prasasti yang menyebutkan, tekstil menjadi salah satu hadiah kepada pejabat kerajaan atas diberikannya anugerah sima atau pembebasan pajak.
Bahkan, ada prasasti yang memuat kata wdihan (pakaian pria) dan kain atau ken (pakaian perempuan).Juga ada kata kalambi (pakaian atas) dan singhel (pakaian khusus untuk golongan pendeta, terbuat dari kulit kayu). Kitab Tantu Panggelaran mengungkapkan, singhel dibuat dari daun lalang, daluwang, atau babakaning kayu.
Arkeolog Edhie Wurjantoro dalam penelitiannya—seperti diungkapkan dalam “Wdihan dalam Masyarakat Jawa Kuna Abad IX-X M” (1986)—menemukan ada berbagai jenis wdihan yang dijumpai dalam sumber prasasti. Setiap golongan masyarakat, termasuk raja, mengenakan jenis wdihan yang berbeda.
Begitu pula dengan kain atau ken, ada beberapa jenis dan pemakainya berbeda-beda menurut jenisnya. Jenis ken untuk istri pejabat tinggi, misalnya, berbeda dengan ken untuk istri pejabat menengah, pejabat rendahan, dan masyarakat umum.
Tapi, memang, tidak ada informasi dari prasasti-prasasti itu yang menyebutkan apa saja jenis kain yang digunankan pada masa itu. Berita Tiongkok dari masa Dinasti Song (960-1279) hanya menyebutkan, penduduk Jawa memelihara ulat sutera dan menenun kain sutra halus. Diungkapkan pula, banyak penduduk memakai baju dari katun. Sebagian dari mereka mengenakan pakaian yang menutupi tubuhnya dari dada sampai ke bawah lutut, dengan cara dibelitkan ke sekeliling tubuh.
Apakah mode sudah dikenal pada masa itu? Ya. Karena ada prasasti yang memuat kata pawdihan yang kira-kira artinya ‘penenun’ atau ‘tukang jahit’, misalnya di Prasasti Patakan dari abad ke-11 pada masa pemerintah Raja Airlangga dari Kerajaan Kahuripan.
Adapun dari relief Candi Borobudur, yang dibuat pada abad ke-9, dapat ditemukan gambaran bangsawan dan rakyat, baik laki-laki dan perempuan, yang membiarkan bagian dadanya terbuka. Juga ada relief yang menggambarkan bangsawan yang mengenakan pakaian tipis, kemungkinan dari sutera atau katun.Dari Jawa
DENGAN uraian di atas jelaslah bahwa masyarakat Nusantara, terutama di Jawa, sudah memiliki tradisi tekstil yang panjang. Juga sudah mengenakan busana dari tekstil. Dan, kuat dugaan, kebaya memang awalnya berasal dari masyarakat Jawa, yang kemudian menyebar lewat diplomasi dan interaksi sosial ke wilayah Bali, Sumatera, Melaka, Kalimantan, Sulawesi, sampai ke Sulu dan Mindanao di Filipina, sebagaimana diungkapkan dalam buku Re-orienting Fashion: The Globalization of Asian Dress yang disunting S. A. Niessen, Carla Jone, dan Ann Marie Leshkowich (2003); makalah yang ditulis Victoria Cattoni, “Reading The Kebaya” (2004), dan; buku Indonesian Textiles yang ditulis Michael Hitchcock (1991).
Kebaya pada masyarakat Jawa yang dikenal seperti sekarang telah dicatat juga oleh Sir Thomas Stamford Raffles pada tahun 1817, dalam bukunya yang fenomenal The History of Java. Raffles mencatat, kebaya dibuat dari bahan sutera, brokat, dan beluderu (velvet), dengan bukaan tengah blus diikat dengan bros, bukan dengan kancing dan lubang kancing, dengan pakaian dalam berupa kemben. Kerahnya berbentuk “V”.
Namun, pada masa invasi Inggris di Jawa itu, di bawah pemerintahan Raffles, pemakaian kebaya di masyarakat Jawa tersaingi dengan model gaun terusan ala Eropa. Pemakaian kebaya hanya dikenakan oleh orang Jawa pada momen-momen tertentu.
Kebaya mulai berangsur-angsur digemari lagi ketika Pemerintah Kolonial Belanda mulai berkuasa. Menurut Jean Gelman Taylor dalam artikelnya, “Kostum dan Gender di Jawa Kolonial Tahun 1900-19940”—dalam buku Outward Appearances: Trend, Identitas, Kepentingan yang disunting Henk Schutle Nordholt (2005)—kebaya menjadi busana perempuan bagi semua kelas sosial, termasuk dikenakan oleh para perempuan Belanda. Kebaya seakan menjadi busana wajib pagi hari bagi para perempuan Belanda di Hindia Belanda pada masa itu.
Bahkan, seperti dicatat Catenius-van der Meijden dalam bukunya, Naar Indië en terug: Gids voor het gezin, speciaal een vraagbaak voor dames (tanpa tahun), para perempuan Belanda pada akhir abad ke-19 yang akan ke Hindia Belanda disarankan untuk membawa kebaya dan sarung. Kebaya dan sarung itu sebaiknya juga dibeli di Hindia saja. Karena, kata Catenius, ‘kebaya yang dibeli dengan harga mahal di Belanda terlihat konyol ketika dikenakan di Hindia’. Pada buku itu juga diingatkan agar tidak membawa pakaian terlalu banyak karena di Hindia ‘semuanya sangat murah dibandingkan di Belanda.’
Kebaya yang dikenakan para perempuan Belanda ini dikenal dengan nama kebaya Indo. Potongan dan gaya kebayanya mirip dengan kebaya Jawa. Namun, umumnya, bagian lengan kebaya Indo lebih pendek dari kebaya Jawa. Bahannya dari katun dan dihiasi dengan renda, yang umumnya diimpor dari Eropa. Untuk daleman, mereka tidak lagi mengenakan korset, namun pakaian dalam yang ringan dan nyaman. Kebaya katun putih biasanya dikenakan di pagi atau siang hari. Untuk malam, mereka mengenakan kebaya lazimnya mengenakan kebaya berwarna hitam berbahan sutera.
Kebaya Jawa memang simpel. Potongannya lurus dan sederhana, dengan leher “V”. Umumnya kebaya Jawa dibuat dari kain halus semi-transparan, dengan hiasan bunga, bordir, atau manik-manik. Pakaian dalamnya korset, bra, atau kamisol. Bahan lain yang digunakan untuk kebaya Jawa adalah katun, brokat, sutera, atau beluderu.
Ada juga jenis kebaya yang disebut sebagai kebaya Kartini, yakni model kebaya yang biasanya digunakan perempuan bangsawan Jawa pada masa hidup Kartini di awal abad ke-20. Ini juga mirip dengan kebaya Jawa umumnya. Bedanya, bahannya dari kain halus yang tidak transparan, yang umumnya polos. Hiasannya juga minim. Hanya jahitan atau tali pengaman di pinggir-pinggirnya. Potongan kerahnya berbentuk “V”, dengan berbentuk vertikal, yang membuat postur pemakainya terkesan lebih tinggi. Panjang kebaya ini menutupi pinggul.
Model yang lain adalah kebaya kutubaru. Modelnya sangat mirip dengan jenis kebaya lain. Bedanya, ada kain tambahan yang disebut beff untuk menghubungkan sisi kiri dan kanan kebaya di dada dan perut. Dengan demikian, kerahnya berbentuk persegi atau persegi panjang. Biasanya, pemakai kebaya ini mengenakan stagen atau korset hitam berlapis karet, sehingga pemakainya terlihat lebih langsing. Kebaya kutubaru berasal dari Jawa Tengah.Ada pula kebaya Bali. Kebaya ini sebenarnya mirip juga dengan kebaya Jawa. Namun, bedanya, kebaya Bali memiliki garis leher “V” dengan kerah dilipat, yang kadang dihiasi tali pengikat. Kebaya Bali biasanya pas-ketat di badan, dengan bahan dari kain semi-transparan atau polos warna-warni, dari katun atau brokat, berpola dengan jahitan bunga atau bordir. Kebaya Bali juga bisa menambahkan kancing di bukaan depan. Kebaya Bali juga biasanya dikenakan dengan sabuk kebaya seperti obi, untuk membungkus pinggang. Lengannya pun lebih pendek dari lengan kebaya Jawa. Karena, selain digunakan untuk upacara keagamaan, kebaya bali juga lazim dikenakan untuk kegiatan sehari-hari.
Kebaya Sunda lain lagi. Kerahnya berbentuk “U”, cenderung melengkung lebar untuk menutupi bahu dan dada. Bagian bawahnya juga sangat panjang, dengan pinggir menggantung menutupi pinggul dan paha. Kainnya semi-transparan, dengan jahitan bunga atau bordir.
Masyarakat Tionghoa Peranakan di Jawa pada masa kolonial Belanda juga kerap menggunakan kebaya. Awalnya, mereka meniru kebaya Indo yang terbuat dari kain putih mahal yang dihias renda. Pada tahap selanjutnya, mereka membuat kebaya kerancang, yang juga masih sangat mirip dengan kebaya Indo. Bedanya, renda diganti kerancang atau cutwork (kain berlobang kebaya bordir agar terlihat
seperti renda). Kemudian, mereka membuat kebaya sulam (bordir), yakni berbahan kain tipis warna-warni dengan gambar besar yang disulam. Gambarnya adalah flora dan fauna yang memiliki nilai simbolis dalam budaya Tiongkok, seperti teratai, bunga peony, burung phoenix, dan ayam.
Kebaya ini dikenal sebagai kebaya encim, yang diambil dari kata encim atau enci dalam bahasa Tionghoa, yang mengacu ke perempuan Tionghoa yang sudah menikah. Umumnya, yang mengenakan adalah perempuan Tionghoa di kota-kota pesisir di Jawa, antara lain Semarang, Lasem, Tuban, Surabaya, Pekalongan, dan Cirebon. Bahan kainnya biasanya yang ringan, seperti sutera atau kain halus lain, berwarna cerah, dengan bordir yang besar dan halus.
Di Malaysia dan Singapura, kebaya encim dikenal sebagai kebaya nyonya. Biasanya, kebaya ini dipadupadankan dengan sepatu manik-manik (kasut manek) berbahan sutera dan dilukis dengan motif Tiongkok.
Pada masa pendudukan Jepang, pamor kebaya di Indonesia, terutama di Jawa, meredup. Masalahnya, jalur perdagangan tekstil dan benda-benda lain yang berkaitan dengan busana diputus oleh pemerintah fasis Jepang.Ibu Fatmawati
Setelah Indonesia merdeka, pemakaian kebaya kembali marak, terutama karena Ibu Negara Fatmawati kerap mengenakan kebaya dalam berbagai acara. Bahkan, ketikan mendampingi Presiden Soekarno kunjungan kerja ke Filipina pada tahun 1951, Ibu Fat juga mengenakan kebaya dalam acara resmi kenegaraan. Sejak itulah kebaya menjadi semacam busana nasional bagi perempuan Indonesia.
Pada masa Orde Baru, dalam lokakarya tahun 1978 yang diikuti utusan dari
27 provinsi di Indonesia ditetapkan empat kriteria busana nasional Indonesia. Kriteria tersebut adalah, pertama, tidak mencerminkan kedaerahan; kedua, bisa dimiliki oleh setiap lapisan masyarakat; ketiga, mudah didapat, mudah perawatan, dan harganya terjangkau, dan; keempat, tidak lepas dari unsur etika serta estetika berbusana. Yang kemudian disepakati sebagai busana nasional perempuan Indonesia adalah kebaya, bukan baju kurung, baju bodo, atau baju cele. Baju kurung tidak dipilih karena model ni tidak hanya dipakai di Indonesia, tapi juga menjadi ciri khas Malaysia, Brunei, Thailand, Kamboja, dan Myanmar sehingga kurang istimewa bila berada di komunitas mereka. Akan halnya baju bodo atau baju cele tidak mendapat respons besar dari peserta lokakarya.
Kebaya yang dipilih juga bukan model kebaya panjang. Alasannya: terlalu banyak
memerlukan kain dan, bila dipakai oleh ibu-ibu pejabat, bagian bokong akan kusut dan tidak rapi. Dengan demikina, kebaya pendek menjadi pilihan sebagai busana
nasional perempuan Indonesia. Bawahannya adalah kain panjang yang diwiru. Untuk model kebayanya mengikuti model kebaya yang dikenakan Ibu Negara Republik Indonesia Raden Ayu Siti Hartinah atau Ibu Tien Soeharto di setiap acara resmi nasional dan internasional.
Kemudian, pada tahun 1987 diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 8/1987 tentang Protokol Penataan Busana Nasional yang Harus Dipakai pada Acara Resmi dan Non-resmi oleh Perempuan Indonesia (Ibu Negara). Dalam peraturan pemerintah tersebut dinyatakan, busana nasional bagi perempuan Indonesia terdiri dari kain batik atau sarung yang dipadukan dengan kebaya atau baju kurung serta selendang.
Banyak studi tentang kebaya yang dilakukan oleh akademisi dari dalam dan luar negeri. Dengan adanya studi-studi itu dapat dikatakan, kebaya merupakan bagian penting dari gaya berbusana Dunia Timur yang memiliki pengaruh bagi perjalanan fashion dunia. Contoh terbaik dari pengaruh itu adalah pemakaian renda. [PUR]