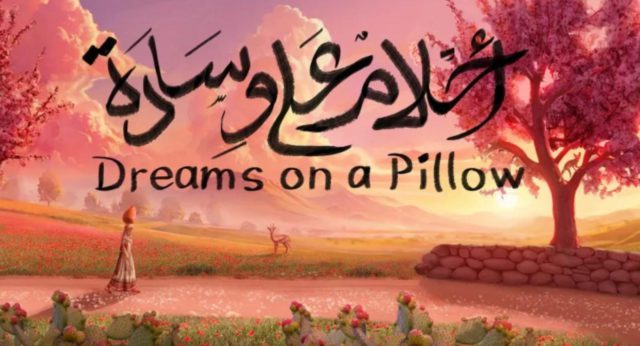Catatan Cak AT:
Di tengah desingan peluru, ledakan bom, dan derita yang tak kunjung usai, siapa sangka seorang developer game di Palestina, Rasheed Abueideh, justru menemukan inspirasi di balik tragedi? Dengan crowdfunding sebagai andalan pendanaan, Abueideh dan timnya sedang mengembangkan game baru berjudul Dreams on a Pillow.
Bagaimana ini mungkin? Bukankah perang seharusnya hanya menghasilkan berita tentang keruntuhan, bukan karya seni interaktif? Tapi inilah yang membuat Abueideh berbeda: ia tidak hanya membuat game, ia menciptakan cermin digital yang memantulkan realitas brutal pendudukan dan eksodus paksa selama Nakba 1948.
“Dapatkah sebuah video game membuatmu merasakan beratnya sejarah?” tanya Abueideh dalam wawancara dengan Al Jazeera. Pertanyaan inilah inti dari Dreams on a Pillow, yang jawabanya ia rangkai di situ. Game ini mengangkat kisah Omm, seorang ibu muda yang melarikan diri dari pembantaian di Tantura, kini wilayah Israel.
Sebagai gambaran, Tantura yang kini dikenal sebagai Dor, terletak di pesisir utara Israel, bersebelahan dengan Laut Mediterania. Desa ini berada 8 km di selatan kota Haifa, di pesisir barat wilayah yang kini menjadi bagian dari Israel. Sebelum peristiwa Nakba pada tahun 1948, Desa nelayan ini kaya dengan kehidupan budaya dan ekonomi.
Omm berlari ke utara menyusuri pantai. Ia melewati desa demi desa, kota demi kota, ke Atlit – sebuah kota kecil dengan pelabuhan dan benteng tua dari masa Perang Salib – terus ke Haifa dengan pelabuhan internasionalnya, lanjut ke Acre (Akko), kota bersejarah yang kaya akan peninggalan dari zaman Ottoman dan Perang Salib, hingga Nahariya.
Mungkin ia mencapai Rosh Hanikra, kota paling utara di pesisir, dekat perbatasan Lebanon, dengan gua-gua kapur yang terkenal. Dalam game yang bukan hanya menghibur ini, Omm berlari menyusuri pantai ini sambil membawa sesuatu yang disangka bayi —ternyata hanya bantal. Plot yang tragis, tapi juga ironis: sebuah simbol keamanan (bantal) berubah menjadi bukti kehilangan yang paling mendalam.
Dalam gameplay-nya, yang juga memuat bobot sejarah dan perlawanan itu, pemain diajak memahami trauma psikologis melalui mekanik yang unik. Saat Omm memegang bantal, ia merasa aman karena merasa itu bayinya. Namun ketika bantal itu diletakkan, ia dihantui rangkaian mimpi buruk dan halusinasi.
Membawa para pemain seolah sedang berada dalam simulasi perasaan para pengungsi Palestina, game ini memadukan elemen nostalgia kehidupan Palestina sebelum 1948 dengan mimpi buruk yang mengiringi tragedi Nakba. Anda tahu, Nakba merupakan permulaan dari rangkaian genosida struktural yang dilakukan Israel hingga kini.
Tragedi Nakba (al-Nakba dalam bahasa Arab yang berarti “malapetaka”) terjadi pada tahun 1948, ketika lebih dari 700.000 warga Palestina diusir atau melarikan diri dari tanah air mereka akibat pendirian negara Israel. Peristiwa ini terjadi bersamaan dengan Perang Arab-Israel 1948 yang meletus setelah deklarasi kemerdekaan Israel pada 14 Mei 1948.
Nakba bukan hanya sekadar pengusiran massal, tapi juga diikuti penghancuran lebih dari 500 desa Palestina, pembantaian massal di beberapa tempat seperti Deir Yassin, serta pencaplokan tanah-tanah Palestina. Konflik ini menyebabkan trauma berkepanjangan karena kehilangan rumah, tanah, dan akses ke warisan budaya mereka.
Hingga hari ini, Nakba dianggap sebagai akar dari konflik Palestina-Israel yang belum selesai. Pengungsi Palestina, yang jumlahnya sekarang mencapai jutaan, masih tersebar di berbagai kamp di Timur Tengah, dengan hak mereka untuk kembali ke tanah air tetap menjadi isu yang diperdebatkan dalam politik internasional.
Abueideh menggambarkan itu semua di gamenya. Untuk dana, ia berhasil mengumpulkan $218.272 melalui platform crowdfunding LaunchGood. Jumlah ini cukup untuk memulai pengembangan tahun pertama, termasuk gaji dan pembuatan aset. Namun perjalanan menuju pendanaan tidaklah mulus.
Banyak platform besar menolak proyek ini karena tema politiknya yang sensitif. Ironisnya lagi, di era digital yang katanya bebas, konten pro-Palestina kerap diberangus. YouTube, Instagram, hingga Netflix terlibat dalam kontroversi atas penghapusan konten Palestina. Tapi Abueideh memilih melawan. Melalui Dreams on a Pillow, ia berkata kepada dunia: “Kami tidak hanya bertahan; kami menciptakan.”
Jika kita menggali lebih dalam, game ini juga sebuah satire. Bayangkan seorang ibu Palestina lari dari pembantaian hanya untuk menyadari bahwa ia memeluk bantal, bukan bayinya. Ini merupakan bentuk refleksi atas absurditas perang: kehilangan begitu besar hingga realitas pun terasa seperti parodi suram.
Dan bukankah absurd pula bahwa sebuah game, yang biasanya dibuat untuk hiburan, kini menjadi alat edukasi politik? Atau bahwa di tengah perang genosida, masih ada ruang untuk pixel art, coding, dan desain level? Ini membawa renungan pada kita yang hidup di alam bebas, bahwa kreativitas bisa tumbuh bahkan di lingkungan yang sulit.
Abueideh sekaligus membuktikan bahwa video game dapat menjadi bentuk perlawanan budaya. Dalam proyek sebelumnya, Liyla and the Shadows of War, ia menggambarkan perjuangan keluarga Palestina melawan kehancuran selama serangan Israel di Gaza pada 2014. Game tersebut, meski ditolak oleh Apple pada awalnya, akhirnya sukses besar dengan jutaan unduhan.
Namun Dreams on a Pillow melangkah lebih jauh. Tidak hanya mengisahkan kehancuran, tetapi juga kehidupan Palestina sebelum Nakba: sebuah tanah yang penuh budaya, tradisi, dan keindahan. Melalui game ini, Abueideh ingin menantang narasi “tanah tanpa rakyat untuk rakyat tanpa tanah” yang selama ini disuarakan propaganda Zionis.
Sambil kita tunggu wujudnya, kita dapat berkata bahwa Dreams on a Pillow bukan sekadar game. Ia manifesto digital, pengingat bahwa kreativitas tidak dapat dihancurkan bahkan oleh bom. Dalam dunia di mana Palestina seringkali dikurangi menjadi statistik korban, game ini mengembalikan suara dan cerita kepada mereka.
Mungkin hari ini dan besok-besok, ketika gencatan senjata antara Israel-Hamas berlaku, dunia akan sejenak menarik napas. Namun bagi Abueideh dan rakyat Palestina, perjuangan tetap berlanjut —baik di medan perang maupun di layar komputer.
Dan siapa tahu, mungkin suatu hari, pixel-pixel kecil ini akan membantu menggoyang narasi besar yang selama ini menindas mereka.
Cak AT – Ahmadie Thaha | Kolumnis