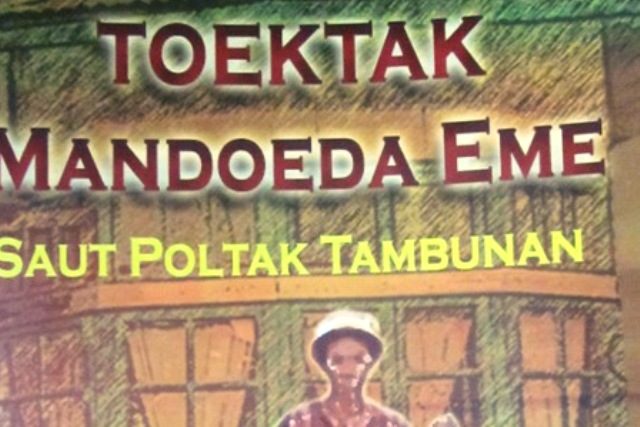Koran Sulindo – Kumpulan cerita pendek karya Saut Poltak Tambunan berjudul Toektak Mandoeda Eme merupakan buku ke-17 yang ditulisnya dengan bahasa Batak Toba. Pria kelahiran Balige, Sumatera Utara, 28 Agustus 1952 itu sengaja menuliskannya dalam bahasa Batak Toba sebagai warisan kepada generasi muda Sumatera Utara. Pasalnya, banyak generasi muda Sumut di perantauan yang tidak memahami bahasa Batak dengan baik. Bahkan, ada yang sudah tidak bisa atau mengerti bahasanya.
“Banyak orang Batak KW1, bisa bicara tapi sekenanya, yang kadang tercampur-campur dengan bahasa Indonesia. Terlihat janggal, sebenarnya salah dalam penggunaanya. Juga ada orang Batak KW2, tahu arti bahasa Batak tapi nggak bisa mengucapkannya. Inilah salah satu keprihatinan,” ujar Saut dalam bedah buku Toetak Mandoeda Eme, di Gedung Pertemuan Op Tobok Sianipar, Jalan H. Dogol, Durensawit, Jakarta Timur pada Sabtu (30/6) lalu.
Kumpulan cerpen yang ditulis Saut itu lebih mengisahkan kehidupan sehari-hari orang Batak di kampung halaman, dan perantauan. Ia menuliskan tradisi orang Batak yang merantau tetapi tetap membawa bahasa, marganya (fam), gereja (huria) dan lapo-nya (warung). Adat istiadat adalah bagian yang tidak bisa diabaikan dari kehidupan orang Batak, baik di daerah asal atau di perantauan. Dalam kehidupan masyarakat Batak, adat adalah satu kesatuan yang utuh, baik bahasa, marga, silsilah (tarombo). Bahkan masyarakat Batak Kristen dalam tata peribadatan menggunakan bahasa Batak sebagai sarana beribadah.
Namun, paradigma ini belakangan agak bergeser bagi masyarakat Batak di perantuan yang terkesan disengaja seperti ‘malu’ menjadi orang Batak. Dalam bukunya itu, Saut ‘menyentil’ pergeseran tata nilai Batak itu. Kendati tidak menyinggung nama, dalam buku kumpulan cerpen yang lebih mengedepankan bahasa bertutur itu, Saut sedang melakukan kritik sosial dalam paradigma orang Batak terutama di era digital ini. Seolah-olah bahasa Batak sudah mulai ditinggalkan. Padahal, bahasa adalah akar dari budaya orang Batak.
Marga bagi orang Batak bukan sekadar identitas. Namun, marga juga membangun hubungan kekerabatan, dan mencari jodoh. Perlu diketahui, orang Batak tidak bisa sembarangan mencari istri atau suami. Jika sepasang manusia itu semarga, maka tabu untuk melakukan pernikahan, walau tidak ada hubungan darah dekat antara perempuan dan laki-laki yang ingin menjalin kasih. Sampai saat ini adat demikian masih dipegang teguh. Sinamot, atau mahar dalam pernikahan sangat penting. Bila tidak ada kesepakatan dalam sinamot, pernikahan dua mempelai bisa batal.
Namun, Saut juga mengkritik pergerseran nilai juga terjadi dalam hal semarga baik di tanah perantauan maupun di kampung asal orang Batak. Hubungan semarga dinilai hal yang umum. Padahal, nilainya harus ditinjau dari garis keturunan atau silsilah (tarombo). Disitulah letak keunikan orang Batak, hubungan kekerabatan bisa dilihat dari tarombo. Meski jarak semarga itu sudah melewati 20 keturunan, panggilan terhadap seseorang ditentukan dari tarombo. Seseorang yang berusia yang lebih muda bisa saja dipanggil abang, bapak atau paman karena garis tarombonya.
Untuk wanita, panggilannya adalah namboru (adik perempuan bapak, atau wanita yang lebih tua); sedangkan ito panggilan seorang lelaki bagi wanita yang sebaya; sementara eda, sebutan seorang wanita kepada wanita yang sebaya, atau perempuan saudara suami; lalu tulang juga istilah panggilan kepada adik atau kakak ibu; kemudian nantulang panggilan kepada istri tulang; untuk panggilan uda, yang disematkan kepada adik ayah; dan bapak tua ditujukan kepada kakak ayah. Pemanggilan opung bagi orang yang sudah tua segi usia, atau segi tarombo. Semua istilah ini dituliskan Saut dalam bukunya itu.
Jauh sebelum Indonesia berdiri sebagai sebuah negara, orang Batak, menurut Saut, sudah mengenal demokrasi. Itu dikenal sebagai dalian natolu. Hubungan kekerabatan dan saling menghargai dan menghormati dilihat dari dalian natolu, yakni somba marhula-hula (hormat kepada pihak istri), elek Marboru (dimana harus bisa mengayomi pihak wanita) dan manat mardongan tubu (bersikap saling menghargai kepada teman semarga). Karenanya dalam dalian natolu, pemanggilan bagi masyarakat Batak, paman sangat dihargai. Bahkan, posisi paman itu tidak ubahnya seperti raja yang harus dihormati oleh rakyatnya. Dalam pernikahan atau pesta, paman menempati posisi yang sangat penting.
Lebih lanjut, dalam pesta pernikahan atau pesta lainnya, yang melayani dalam acara hajatan itu adalah pihak perempuan yang semarga dengan perempuan tersebut. Jadi dalam pesta adat Batak dilihat dari tarombo, tidak dilihat dari kekayaan atau pangkat yang dimilikinya.
Dari segi religi, khususnya masyarakat Batak Kristen. Merantau tidak lupa membawa gerejanya, tidak heran di daerah lain adanya gereja-gereja suku Batak bertaburan. Contohya, Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) dan Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS).
Sementara itu, Kepala Badan Pembina dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Dekdikbud), Ganjar Harimansyah mengemukakan, bahasa Batak memiliki dialek yang berbeda antara puak-puak satu dengan yang lain, antara Batak Toba dengan Batak Karo berbeda bahasa, meski satu daerah Sumatera Utara, itulah kekayaan kebinekaan yang dimiliki Indonesia.
Ganjar mengungkapkan, ada beberapa bahasa di Papua yang hampir punah. Menurutnya, ini tidak boleh terjadi karena bahasa adalah kekayaan yang harus dilestarikan. Ia karena itu mengapresiasi penulisan buku kumpulan cerpen Toetak Mandoeda Eme. Saut dinilai sangat produktif, terlebih sebanyak 17 buku sudah dituliskan dengan bahasa sastra Batak. Tidak heran Saut yang kini menikmati hari tuanya meraih penghargaan RANCAGE 2015 atas karya Si Tumoing. Untuk meraih itu tidak dikerjakan dalam satu hari ibarat kisah Raja Bandung Bondowoso yang ingin membangun 1.000 candi hanya dalam semalam sebagai syarat mempersunting Roro Jongrang. Saut meraih penghargaan sastra itu karena telah berkiprah di dunia sastra sejak 1973. Namun, sebuah kebanggaan tersendiri bagi Saut, karyanya akhirnya diakui lewat penghargaan tersebut.
Anggota DPRD DKI Jakarta Sereida Tambunan mengemukakan, sudah puluhan tahun dirinya tinggal di Jakarta. Diakui Serieda, ia tidak fasih lagi menggunakan bahasa Batak yang benar dan tepat. Tanpa malu, ia mengakui sebagai orang Batak KW1 karena berbicara bahasa Batak sekenanya.
Dikatakan Sereida, membaca buku Saut dalam bahasa Batak itu bukan perkara mudah. Untuk memahaminya, politikus wanita dari PDI Perjuangan itu harus terlebih dulu menerjemahkannya. “Bahasa Batak bukan sekedar kata-kata, tetapi ada satu kalimat ada makna yang mendalam di dalamnya. Itulah bahasa Batak,” ujar Sereida dengan kagum. [RLJ]