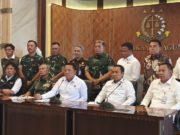Koran Sulindo – Mereka menamakan dirinya sebagai Orde Baru dan memberi cap pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno sebagai Orde Lama. Itu bukan sekadar cap untuk membedakan dua masa kepemimpinan, tapi sesungguhnya stigma negatif yang bertendensi memutus tali sejarah dan menistakan apa yang mereka anggap sebagai Orde Lama. Mereka semua bekerja di bawah kontrol Jenderal (Purn.) Soeharto.
Berbagai cara mereka lakukan selama lebih dari 30 tahun, terutama dengan cara-cara kejam—yang sungguh sulit dibayangkan bisa dilakukan manusia. Tumpas kelor, begitulah orang menamakan cara yang mereka lakukan terhadap apa yang mereka cap sebagai Orde Lama dan terhadap siapa pun atau pihak mana pun yang diasumsikan dapat merongrong kekuasaan mereka. Bahkan, kartu tanda penduduk dari orang yang mereka curigai pun diberi tanda khusus.
Siapa pun dan pihak mana pun bisa mereka anggap musuh yang harus dibasmi. “Saya merasa di titik dasar kehinaan di Indonesia pada masa Orde Baru,” kata sastrawan besar Indonesia, Pramoedya Ananta Toer, saat diwawancarai utusan Kementerian Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Belanda, Kees Snoek, dan dimuat dalam buku Saya Ingin Lihat Ini Berakhir (2008).
Pada masa rezim Soeharto, Pram ditahan di Pulau Buru selama sepuluh tahun. Ia juga disiksa dan dianiaya. Tanpa pernah ada proses hukum dan pengadilan. “Berdasarkan pengalaman saya sendiri, Soeharto adalah penjahat kemanusiaan. Setiap orang di mana pun di seluruh dunia berhak menuntut Soeharto,” kata Pram saat ceramah di George Washington University, Amerika Serikat, April 1999, sebagaimana diberitakan Jawa Pos.
Jutaan orang Indonesia mengalami nasib seperti Pram di masa pemerintahan Presiden Soeharto. Bahkan, Presiden Soekarno pun bukan hanya dipereteli kekuasaannya, tapi juga diasingkan di negeri yang telah ia perjuangkan dan ia proklamasikan kemerdekaannya ini.
Lewat cara yang seolah konstitusional, melalui Sidang Istimewa MPRS pada 7 Maret 1967, Soeharto menabalkan dirinya sebagai presiden. Mei 1967, Bung Karno pun dilarang memakai gelar presiden atau kepala negara dan harus keluar dari Istana Negara sebelum tanggal 17 Agustus 1967.
“Kalau meninggalkan istana tidak boleh membawa apa-apa, kecuali buku-buku pelajaran, perhiasan sendiri, dan pakaian sendiri. Barang-barang lainnya seperti radio, televisi, dan lain-lain tidak boleh dibawa,” ungkap Bung Karno seperti dituliskan Maulwi Saelan dalam Dari Revolusi 45 sampai Kudeta 66 (2008).
Menurut kesaksian Sogol Djauhari Abdul Muchid, utusan Kolonel Bambang Widjanarko, salah seorang ajudan Bung Karno, sebagaimana juga ditulis Saelan, Bung Karno meninggalkan Istana Negara sebelum tanggal 16 Agustus 1967. “Keluar hanya memakai celana puaman warna krem dan kaos oblong cap Cabe. Baju piyamanya disampirkan di pundak, memakai sandal cap Bata yang sudah usang. Tangan kanannya memegang kertas koran yang digulung agak besar, isinya Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih.”
Taufiq Kiemas, mantan Ketua MPR yang merupakan menantu Bung Karno, suami dari Ketua PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, semasa hidupnya juga pernah mengatakan, tak ada manusia di Indonesia yang ditindas oleh rezim Soeharto sebagaimana halnya keluarga Bung Karno. “Tapi, apa kita harus terus-menerus mendendam? Forgive, but not forget,” ujar Taufiq Kiemas dalam sebuah kesempatan. Memaafkan, tapi tidak melupakan.
Bung TK, begitu ia dulu biasa disapa, memang bukan sekadar bicara. Ia kemudian juga mendukung penuh dibentuknya Forum Silaturahmi Anak Bangsa (FSAB) dan menjadi pembinanya. Forum yang bermoto “Berhenti Mewariskan Konflik, Tidak Membuat Konflik Baru” ini dibentuk oleh orang-orang yang berkonflik di masa lalu, termasuk keturunan mereka, karena perbedaan politik dan ideologi. Mereka berupaya menghilangkan dendam satu sama lain.
Memaafkan memang perbuatan mulia dan memaafkan, kata Mahatma Ghandi, adalah tanda kekuatan. Orang yang lemah tak mampu memaafkan. Namun, bukan berarti sejarah harus dilupakan. Sejarah harus dijadikan pelajaran dan pijakan dalam upaya mencapai masa depan gemilang dan menghindari yang kelam agar tak berulang. [PUR]