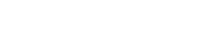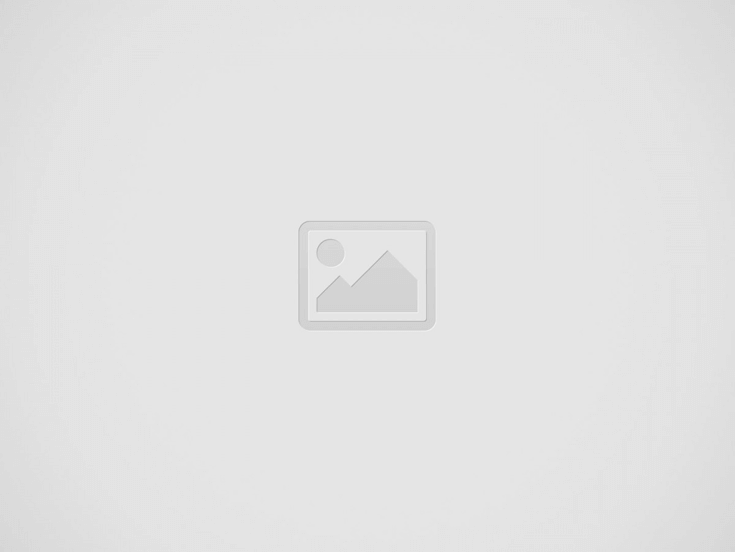Koran Sulindo – Di Surabaya, Megawati memang maju dan bertarung memperebutkan podium pemimpin partai politik yang selama tahun 1993 merebut perhatian (massa). Tekad itu membulat sudah, tidak lonjong atau kotak. Bulat. Sebagaimana hanya dua calon yang paling menonjol meraih podium di Surabaya: Megawati Soekarnoputri vs Budi Hardjono. Usia Megawati saat itu 46 tahun.
Yang bingung tentu saja pemerintah. Juga, jenderal-jenderal di Jakarta dan di daerah. Melihat dukungan kepada Megawati menguat di akar rumput, mau tidak mau pemerintah via para jenderal merapatkan barisan untuk memberi dukungan kepada figur yang mudaratnya dipandang kecil terhadap kekuasaan “pembangunanisme” Soeharto.
Jalan paling rasional adalah mendukung Hardjono. Padahal, sosok ini kerap bersuara lantang di parlemen ketimbang Mega yang hening.
Bagi pemerintah, sevokal-vokalnya Budi Hardjono, tetaplah dianggap sebagai berisik yang biasa dan tidak berbahaya. Berbeda dengan diam dan heningnya Mega yang dipandang sebagai magma. Panasnya yang membara bukan di permukaan, melainkan dalam perut bumi pertiwi.
Kemunculan Mega jelas di luar skenario. Terutama, kebiasaan partai ini sejak fusi pada 1973. Skenario yang menjadi adab politik adalah calon yang menjadi pemimpin partai mestilah yang direstui. Paling tidak, figur yang bisa “dipegang”.
Megawati lain. Ia politisi yang dingin yang lahir dari pengucilan yang sistematis atas politik ayahnya. Orang menyebutnya karisma Sukarno diwarisi Mega. Massa rindu kembali pasangnya politik Sukarno lewat keluarga batihnya. Kerinduan ini berbenturan dengan kehendak pemerintah yang ingin menghabisi karier keluarga ini dalam konstelasi politik nasional.
Sebagai magma dalam gunungan politik, Megawati tetaplah menjadi pusat perhatian. Yang kasak-kusuk justru yang berada dalam radius magma itu. Termasuk, betapa ramainya kejadian yang mengiringi prosesi kedatangan peserta kongres luar biasa (KLB) di Surabaya ini.
Peserta dari cabang yang menjadi pendukung fanatik Megawati dipersulit sedemikian rupa keikutsertaannya lewat “politik administrasi” yang membutuhkan restu dari jenderal-jenderal setempat. Bahkan, utusan dari Sulawesi mesti mengeluarkan “Deklarasi Umsini” dari kapal milik Pelni, KMP Umsini.
Sebagai magma, sekali lagi, Megawati tidak “tersentuh”. Ia tidak mendapat tekanan secara pribadi. Pemerintah juga tidak terus terang melakukan intervensi kepadanya untuk menghentikan langkah politik yang sudah diayunkannya. Sikap majunya Mega jelas, kongres adalah ikhtiar menegakkan konstitusi partai di mana tak ada satu pun anasir dari luar yang memiliki hak turut campur.
Megawati tahu betul ia memegang kendali isu. Bahwa inilah saatnya partai hasil bonsai pemerintah Orde baru sedemikian rupa dari induknya ini, Partai nasional Indonesia (PNI), kembali ke trah Sukarno. Oleh karena itu, langkah pertama yang dilakukan Mega saat pertama kali menginjak bumi Surabaya yang heroik itu adalah melakukan peziarahan ke makam ayahandanya, Ir. Sukarno, di Blitar.
Sebetulnya, itu tindakan sederhana. Bahkan, khas masyarakat bawah. Terutama, kalangan wong cilik Jawa Timur yang “bermazhab” NU maupun kejawen. Ziarah kubur adalah adab yang hidup menghargai yang sudah mendahului. Juga, sarana berkomunikasi dengan pihak yang berada di dunia lain.
Namun, peziarahan ini bukan peziarahan yang biasa lantaran momentumnya adalah politik yang kritikal berkait dengan menaiknya keyakinan publik bahwa ada atau tidaknya restu pemerintah yang berpusat di Jakarta tidak menjadi persoalan. Yang penting, “restu” dari Blitar bisa didapatkan. Lagi pula, sebagaimana kata Mega, restu itu mengikuti panggilan hati nurani, bukan diminta. Ya, frase “restu” memang khas dalam perpolitikan kita. Sejak lama hingga kini.
Poros Blitar-Surabaya adalah poros politik biografis Sukarno. Surabaya adalah tanah tumpah darah sang pendiri Republik, sementara Blitar adalah tanah kembalinya Sang Proklamator. Jika Surabaya adalah sunrise, Blitar adalah sunset. Perlintasan Megawati antara Surabaya-Blitar-Surabaya adalah menapaktilasi memori politik sang surya bagaimana tokoh politik terbesar Indonesia ini mengembangkan karakter dasarnya untuk mengerek bendera revolusi pembebasan nasional atas bangsanya.
Sebagaimana ritus peziarahan yang hening, seperti itu pula adab politik Megawati dalam gelanggang panas KLB. Karakternya yang tidak ingin adu urat leher di ujung mikrofon atau atraksi lobi yang aktif terejawantahkan dalam arena sepanjang kongres. Pendeknya, ia bukan politisi urakan dan menyukai kasak-kusuk.
Cara berpolitik seperti Mega ini, mohon maaf, sering jadi bahan ledekan lawan politiknya yang isi kepalanya dipenuhi pikiran misoginis. Mega dianggap tidak cocok menjadi politisi. Ia lebih tepat mengurus rumah tangga. Mega yang tumbuh dalam kelamnya politik pemingitan tahu betul bagaimana ruang lingkupnya sangat terbatas. Ia dipagari oleh begitu banyak pembatas, mulai dari pikiran bahwa perempuan tidak layak memimpin hingga sandungan nama besar ayahandanya yang pengaruhnya dipadamkan oleh penguasa. Juga, akses bersekolah ke jenjang lebih tinggi yang dipersempit.
Hingga Guntur Soekarnoputra tampil di Pemilu 1971 menjadi magnet yang mengerahkan massa kaum nasionalis. Putra sulung Bung Karno itu diharapkan menjadi politisi ulung mewarisi garis tangan ayahnya. Mega sama sekali tak masuk dalam hitungan hingga publik terkejut ketika Megawati dengan karakter “khas”-nya itu bisa menembus parlemen di Pemilu 1987.
Di sana, Mega tak mesti harus meniru sang ayah. Sebab, yang dibutuhkan PDI adalah sosok yang mempersatukan friksi tajam yang sulit sekali didamaikan dalam tubuh partai, seperti anasir dari PNI, Murba, IPKI, Partai Katolik, maupun Parkindo. Apalagi, momen naiknya pamor Megawati setelah Filipina melahirkan ibu politik mereka: Cory Aquino.
Sebagai sang ibu pemersatu itulah ia keluar dan naik ke podium tatkala kongres hampir lumpuh lantaran baku hantam dua kubu dan beragam tindakan mengacaukan kongres, seperti mati lampu dan pemaksaan bahwa ketua umum dipilih lewat formatur dan bukan pemilihan langsung.
Di Aula Asrama Haji Sukalilo Surabaya, Megawati berkata dengan mengutip satu kuplet penyair asal India, Swami Vivekananda: “Sudah cukup lama kita menangis, jangan menangis lagi, tegakkan mukamu menjadi manusia sejati, untuk menegakkan kebenaran.”
Kutipan dari pujangga Swami itu adalah panduan tekad bahwa zaman sedang berpihak kepada politik arus bawah. Di Surabaya, nama Megawati dipahatkan. Memang, ia tertunda menjadi pemimpin tertinggi partai. Namun, secara de facto, dialah yang sesungguhnya keluar sebagai pemenang. Ia mendapatkan simpati yang luas dari kader banteng dan sekaligus memberikan sepenuhnya semua harapan tentang pembebasan nasional praktik politik tanpa iklim kebebasan. [Diana AV Sasa, pegiat literasi dan Anggota DPRD Jawa Timur 2019-2024]. Tulisan ini disalin dari situs resmi PDI Perjuangan Jawa Timur.