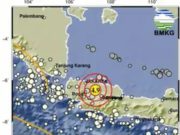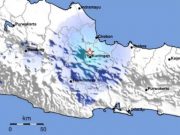Koran Sulindo – Di negara dengan penetrasi ilmu pengetahuan masih terbatas seperti di Indonesia, masyarakat secara natural akan memaknai peristiwa-peristiwa geologis termasuk gempa bumi sebagai kejadian magis dan supernatural.
Contohnya, pernyataan dukungan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) TGH Muhammad Zainul Majdi ke Presiden Joko Widodo untuk periode kedua dan kemudian terjadi gempa bumi beruntun di Lombok, dimaknai sebagai dua peristiwa yang bertalian atau punya hubungan sebab akibat. Fenomena berpikir seperti ini terjadi dalam skala global, bukan hanya di Indonesia.
Tugas para cerdik pandai yang bekerja di universitas, lembaga riset, birokrasi pemerintah, lembaga publik, dan non-pemerintah adalah memberikan penjelasan memadai kepada masyarakat awam tentang fenomena alam yang suatu saat dapat menjadi ancaman sekaligus bencana. Apalagi di Indonesia, secara geologis sangat rentan “dihajar” alam. Selain gempa bumi yang tidak bisa diprediksi waktu kejadiannya, setidaknya Indonesia menjadi tempat bagi 129 gunung api aktif yang bisa meletus setiap saat.
Namun tantangannya adalah bagaimana menjelaskan secara rasional peristiwa gempa, tsunami, banjir, siklon hingga gunung api dan peristiwa alam lainnya.
Niat cerdik pandai menghibur masyarakat dengan pendekatan kerohanian dan keagamaan setelah gempa Lombok, termasuk dilakukan oleh Ketua Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), penting untuk membangun ketegaran mental layak dipuji. Saat hidup berada dalam petaka, berdoa sambil mengutip kitab suci adalah hal yang penting. Toh ke mana lagi Anda harus berpaling ketika institusi formal dan segenap komunitas terbukti gagal memitigasi risiko gempa bumi?
Tetapi untuk sebuah bangsa yang mau berdaya lenting dan tangguh terhadap bencana, para intelektual perlu mengubah strategi komunikasi risiko kebencanaan dari yang bersifat fatalistik menjadi pesan yang memberdayakan dan lebih berdaya lenting dengan berbasis ilmu pengetahuan.
Belajar dari Jepang
Dari sisi desain hunian, suatu ketika, Jepang mencoba membangun model hunian modern khas Inggris yang kemudian runtuh ketika gempa Nobi 1891 yang menimbulkan kematian hampir 8.000 orang. Sedangkan hunian tradisional walau bergoyang saat gempa tapi kerusakan tidak separah rumah modern.
Gempa Nobi memberikan kesempatan bagi Jepang untuk merefleksikan strategi mitigasi gempa yang lebih baik. Tiap kejadian ini menjadi soko guru bagi masa depan. Butuh waktu lebih dari seratus tahun bagi masyarakat Jepang untuk mengubah paradigma menjadi berbasis ilmiah.
Saking seringnya gempa membuat Profesor John Milne, ahli kegempaan dan gunung api yang disewa Pemerintah Jepang dalam kurun waktu 1880-1895, pernah bercanda bahwa Jepang memiliki menu gempa yang tersedia dalam makan pagi, siang, dan malam. Sejak publikasi katalog gempa Jepang yang berisi 8331 gempa yang dideteksi seismograph yang dikembangkan Milne dan timnya, kalangan akademisi dan birokrat Jepang menjadi lebih sadar gempa.
Jepang mampu beralih dari sikap magis dalam memahami bencana menuju respons yang lebih rasional terhadap bencana. Yang menarik adalah kesadaran ini sejak awal tidak tumbuh karena banyaknya angka kematian ataupun peristiwa gempa Nobi 1891 tapi dari bacaan katalog kegempaan yang dihimpun Milne, yang sebagian besar tidak dirasakan oleh indra manusia.
Cerita lengkap bisa Anda baca dalam Earthquake Nation The Cultural Politics of Japanese Seismicity 1868-1930 yang ditulis oleh Greg Clancey.
Strategi Komunikasi Risiko Gempa
Pemerintah Indonesia wajib memikirkan strategi komunikasi risiko gempa secara lebih komprehensif dan tepat sasaran. Demi membangun kultur bangsa yang tegar dan tangguh bencana, semua pihak di Indonesia perlu mengubah strategi komunikasi soal kegempaan maupun fenomena ancaman alam lainnya seperti gunung api, tsunami, siklon, banjir dan ancaman lainnya. Pertanyaannya adalah bagaimana memulainya?
Pertama, perlu mengubah paradigma kegempaan. Tidak semua gempa menyebabkan keruntuhan seperti hunian adat Sasak di Lombok yang tetap gagah berdiri setelah gempa. Mayoritas korban mati saat terjadi gempa karena keruntuhan bangunan rumah yang menimpa penghuninya. Bukan alam yang membangun hunian yang runtuh. Rumah-rumah itu dibangun oleh manusia. Dan rumah dan bangunan kantor publik yang didesain dengan konsep mitigasi gempa, walaupun bisa runtuh, cenderung mampu memberikan kesempatan bagi penghuninya untuk menyelamatkan diri karena strukturnya tidak runtuh seketika.
Kedua, memahami fenomena gempa sebagai fenomena alam semesta yang lumrah. Gempa adalah fenomena geologis planet Bumi, Bulan, dan bintang. Penekanan ini penting!
Sebagian wilayah Bumi adalah wilayah yang secara geologis dinamis. Pergeseran lempeng yang menyebabkan gesekan maupun tumbukan antar lempeng di pertemuan lapisan kerak Bumi dapat menyebabkan gempa yang sebagiannya kita rasakan di permukaan Bumi dengan segenap konsekuensinya. Setiap tahun terdeteksi sedikitnya 500.000 gempa di Bumi, 20% persen di antaranya bisa dirasakan secara indrawi. Hanya 0,02 % (100 gempa) yang berpotensi menimbulkan kerusakan termasuk korban jiwa.
Bulan yang kita lihat hampir setiap purnama juga secara seismologi bersifat aktif. Ya, ada gempa di Bulan. Para peneliti National Aeronautics and Space Administration (NASA) Amerika Serikat bahkan membagi karakteristik gempa di Bulan dalam empat kategori. Pertama, seperti di Bumi, di Bulan ada juga gempa dalam; dan kedua, gempa dangkal. Ketiga, gempa akibat tertimpa meteor. Keempat, gempa karena perubahan suhu kerak Bulan menimbulkan renggangan mendadak akibat ‘membekunya’ sebagian permukaan karenalamanya satu hari di Bulan setara 27 hari di Bumi.
Dalam Tata Surya, terdapat juga kegiatan kegempaan seperti dijumpai pada planet Matahari dan planet lain. Studi tentang fisik geologis Venus memberikan informasi bagi kita terkait fenomena tektonik dan vulkanologis di sana. Kegempaan Mars dan planet lainnya merupakan objek penelitian para ahli dalam beberapa dekade terakhir. Bisa dilihat salah satunya dalam serial Physics of the Earth and Planetary Interiors.
Fokus pada mitigasi dan kesiapsiagaan
Media massa dan akademisi perlu secara sistematis mengkomunikasikan anatomi risiko kegempaan dengan cara yang lebih mutakhir namun sederhana dan dapat dipahami publik.
Dalam penyebaran informasi di media massa dan media sosial, perlu adanya penekanan yang lebih pada dimensi manusia dan kebijakan publik. Fokusnya bukan pada gempanya saja, tapi bagaimana membuat desain bangunan dan infrastruktur yang tahan gempa. Bahwa kerentanan terhadap gempa adalah akibat dari kerentanan fisik bangunan dan infrastruktur yang runtuh menimpa penghuninya.
Kerentanan fisik hunian terjadi akibat kerentanan sosial. Ini buntut dari akses pada pengetahuan tentang standar keamanan minimal bangunan tidak terjadi. Kemiskinan membuat orang tak mampu mengakses teknologi tahan gempa. Hal ini akibat terjadinya kerentanan kelembagaan yang tidak mampu menciptakan tiga hal penting.
Pertama, keterlambatan kelembagaan di daerah dalam mengadopsi regulasi dan standar nasional keamanan gempa menyebabkan kevakuman regulasi di daerah tentang standar pembangunan rumah yang tahan gempa. Hingga 2016, sekitar 40 persen kabupaten belum mengadopsi Undang-Undang Bangunan Gedung yang disahkan pada 2002. Kemampuan daerah mengadopsi standar nasional terkait tata cara perencanaan ketahanan gempa sangat minim.
Kedua, kalau pun ada regulasi di daerah, seringkali tidak ada sistem administrasi publik yang konsisten mengontrol standar keamanan hunian rumah tangga dan infrastruktur lainnya. Implementasi standar minimum pelayanan publik yang akan dimulai 2019 wajib memasukkan jaminan keamanan hunian di daerah rawan bencana.
Ketiga, manakala telah terjadi implementasi mitigasi bencana di tingkat kebijakan dan rumah tangga, maka tindakan sadar yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kesiapsiagaan terhadap kemungkinan gagal struktur hunian saat terjadi bencana. Selalu ada faktor manusia. Tidak ada sistem yang sempurna.
Menjadi rentan terhadap gempa dan bencana sepenuhnya adalah keputusan sosial ekonomi politik, bukan karena alasan magis dan supranatural.
Pesan sains cukup jelas. Bahwa penduduk Indonesia dan Bumi perlu sadar bahwa gempa adalah peristiwa normal dari fenomena planet baik di jagad ini maupun jagad lainnya. Pilihan logis adalah beradaptasi melalui mitigasi kegempaan dalam membangun hunian dan infrastruktur di Bumi. [Jonatan A Lassa,
Senior Lecturer, Humanitarian Emergency and Disaster Management, College of Indigenous Futures, Arts and Society, Charles Darwin University, Australia]. Tulisan ini disalin dari The Conversation Indonesia.