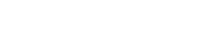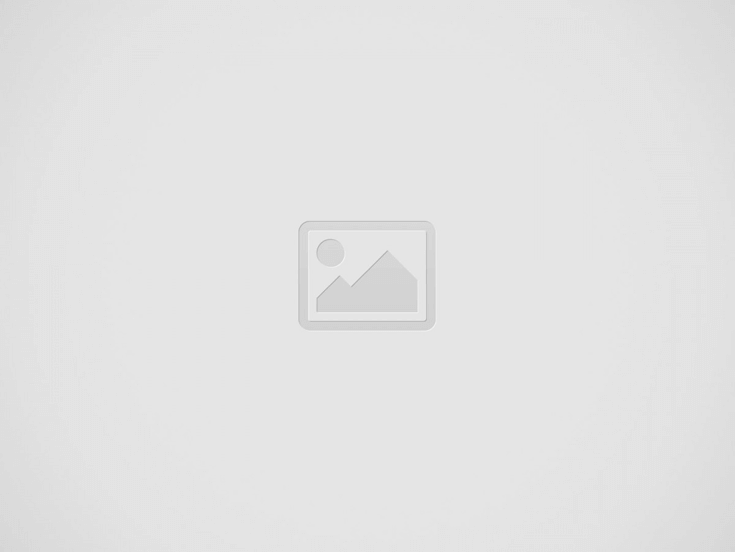LIMA belas hari setelah Imlek atau Tahun Baru Cina, Orang Tionghoa merayakan Cap Go Meh. Selama 2 minggu penuh kaum Tionghoa merayakan Tahun Baru yang dimulai pada hari pertama bulan pertama dalam sistem kalender Cina dan diakhiri dengan Cap Go Meh pada hari kelima belas. Cap Go Meh tidak hanya dirayakan di Indonesia, tetapi juga di negara lain dan dikenal sebagai Festival Lentera atau Festival Lampion.
Perayaan Cap Go Meh di Cina pada zaman dahulu diselenggarakan secara khusus serta tertutup. Tidak setiap orang bisa mengikuti acara tahunan ini, hanya bagi keluarga istana dan kalangan tertentu saja. Semula, perayaan ini dilakukan untuk menghormati Dewa Thai Yai, dewa tertinggi dalam tradisi Dinasti Han (206 SM-221 M).
Dikutip dari tulisan Herman Tan berjudul “Perayaan Cap Go Meh Dalam Tionghoa” Info (27 Oktober 2012), setelah pemerintahan Dinasti Han berakhir, perayaan ini menjadi lebih terbuka untuk umum. Bahkan, pada masa Dinasti Tang (618-907 M), perayaan ini justru menjadi semacam pesta rakyat yang kemudian dikenal dengan nama Festival Yuanxiao atau Festival Shangyuan. Di malam Cap Go Meh, seluruh masyarakat akan tumpah-ruah ke jalan dalam suasana meriah dengan hiasan lampion yang beraneka rupa dibarengi dengan beberapa macam pertunjukan, seperti tarian naga, barongsai, serta pesta kembang api.
Kaum Tionghoa di Indonesia
Asvi Warman Adam dalam Membongkar Manipulasi Sejarah: Kontroversi Pelaku dan Peristiwa (2009) menuliskan, pada masa Orde Baru, orang takut bersembahyang di kelenteng atau melakukan acara budaya Tionghoa lainnya. Memasuki era reformasi seiring lengsernya Soeharto pada 21 Mei 1998, Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang mulai menjabat tanggal 20 Oktober 1999 pun mencabut Inpres No. 14 tahun 1967 yang merugikan warga keturunan Tionghoa di Indonesia itu.
Perayaan tahun baru Imlek mulai senyap sejak Soeharto mengambil alih kuasa sejak 1966. Menurut catatan Tomy Su dalam “Pasang Surut Tahun Baru Imlek” yang terbit di Kompas (8/2/2005), ada 21 beleid beraroma rasis terhadap etnis Cina terbit tak lama setelah Soeharto mendapat Supersemar. Di antaranya adalah kebijakan menutup sekolah-sekolah berbahasa pengantar Cina.
Puncak rasisme rezim The Smiling General ini adalah dengan terbitnya Inpres No. 14/1967 tentang larangan agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina. Sejak itu, perayaan Imlek haram diramaikan di depan publik. Sejalan dengan pelarangan segala bentuk kesenian Tionghoa juga menyangkut pemakaian aksara Cina. Lagu-lagu berbahasa Mandarin pun lenyap dari siaran radio. “Dengan demikian ethnic cleansing atas Tionghoa tidak hanya dalam pengertian fisik, tetapi juga pemusnahan segala hal yang berbau Tionghoa, termasuk kebudayaan dan tradisi agamanya,” tulis Tomy.
Semua itu dilaksanakan dengan alasan yang jelas dibuat-buat: bahwa manifestasi agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina yang berpusat dari negeri leluhurnya dapat menimbulkan pengaruh psikologis, mental, dan moril yang kurang wajar terhadap warga negara Indonesia. Berdasar beleid itu juga sebutan “Tionghoa” lalu berganti jadi “Cina”. Rezim berdalih bahwa semua kebijakan ini adalah demi proses asimilasi etnis yang lebih kaffah. Memang, perayaan Imlek tidak sepenuhnya dilarang. Inpres menitahkan, “perayaan-perayaan pesta agama dan adat istiadat Cina dilakukan secara tidak mencolok di depan umum, melainkan dilakukan dalam lingkungan keluarga”. Sebagaimana kemudian seperti pengakuan Oei Bie Ing bahwa tidak bisa dielakkan komunitas Cina menjadi terpisah dari kelompok masyarakat lainnya. Agaknya juga, gara-gara beleid inilah selama bertahun-tahun kemudian tumbuh stigma komunitas Cina yang eksklusif dan enggan berbaur.
Selama Orde Baru berkuasa etnis Cina tidak diakui sebagai suku bangsa dan dikategorikan sebagai nonpribumi. Sejalan dengan politik kebangsaan Orde Baru, etnis Cina diharuskan mengasimilasikan diri dengan suku-suku mayoritas di tempat dimana mereka bertempat tinggal. Misalnya, jika seorang Cina tinggal di Bandung, mereka harus jadi orang Sunda. Menurut begawan antropologi James Danandjaja, kebijakan itu berdampak lebih jauh daripada sekadar pergantian nama atau agama. Perlahan orang Tionghoa benar-benar melupakan jati dirinya. “Akibat indoktrinasi yang dilakukan dengan sistematis tersebut, kebanyakan orang Tionghoa yang patuh pada politik pemerintahan Orde Baru, dengan sadar atau dengan tidak sadar, telah berusaha melupakan jati diri etnisnya sendiri, sehingga terjadilah autohypnotic amnesia,” tulis James dalam “Imlek 2000: Psikoterapi untuk Amnesia Etnis Tionghoa” yang terbit di majalah Tempo edisi 14 Februari 2000.
Masa-masa suram itu akhirnya berakhir ketika Reformasi bergulir pada 1998. Dalam masa baktinya yang singkat, Presiden Habibie menerbitkan Inpres No. 26/1998 yang membatalkan aturan-aturan diskriminatif terhadap komunitas Tionghoa. Inpres ini juga berisi penghentian penggunaan istilah pribumi dan nonpribumi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Namun Abdurrahman Wahid lah yang kemudian bertindak lebih jauh lagi. Ia muncul membela hak komunitas Cina dengan konsep kebangsaan baru yang diperkenalkannya. Dalam konsep kebangsaan Gus Dur, tak ada yang namanya pribumi dan nonpribumi. Dikotomi semacam itu adalah kesalahan dan gara-gara itu komunitas Cina dinafikan dari nasionalisme Indonesia. Bagi Gus Dur, tak ada yang namanya “keturunan masyarakat asli” di Indonesia, karena bangsa Indonesia dibentuk oleh perpaduan tiga ras, yakni Melayu, Astro-melanesia, dan Cina. Ia sendiri mengatakan dirinya adalah keturunan blasteran Cina dan Arab.
Leo Suryadinata dalam Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Indonesia (2010, hlm. 230) mencatat, “Gus Dur menyebut kelompok-kelompok etnis di Indonesia sebagai ‘orang’ bukan ‘suku’. Ia berbicara tentang orang Jawa (etnis Jawa), orang Maluku (etnis Maluku) dan orang Tionghoa yang kesemuanya adalah orang Indonesia. […] Pada akhirnya ia mendesak ‘penduduk pribumi’ Indonesia untuk menyatu dengan etnis Tionghoa.” Tak hanya berteori, Gus Dur pun merealisasikan gagasannya itu ketika naik jadi presiden pada 1999. Cucu pendiri NU Kiai Hasyim Asy’ari yang sejak lama dikenal sebagai pluralis itu menganulir Inpres No. 14/1967 dengan menerbitkan Inpres No. 6/2000. Sejak itulah, komunitas Tionghoa bebas kembali menjalankan kepercayaan dan budayanya.
Inpres yang terbit pada 17 Januari tersebut membawa suka cita yang telah lama surut. Tahun baru Imlek tahun itu, yang jatuh pada 5 Januari, dirayakan dengan cukup megah di kompleks Museum Fatahillah Jakarta.
Pada 9 April 2001, dengan Keppres No. 9/2001, Gus Dur meresmikan Imlek sebagai hari libur fakultatif. Dengan kebijakan-kebijakan inklusif itu tidak berlebihan jika kemudian pada 10 Maret 2004 -bertepatan dengan perayaan Cap Go Meh di Klenteng Tay Kek Sie- masyarakat Tionghoa di Semarang menyematkan julukan “Bapak Tionghoa” kepada Gus Dur.
“Maka setiap kali menjelang perayaan Imlek, saya selalu ingat Gus Dur. Sejak menjabat sebagai Ketua Nahdlatul Ulama, tiada henti Gus Dur membela penganut aliran kepercayaan dan pemeluk Konghucu untuk memperoleh haknya sebagai warga negara,” tulis F.X. Triyas Hadi Prihantoro dalam surat pembacanya yang ditayangkan Kompas (5/2/2008). [*]