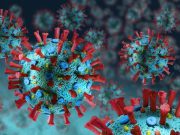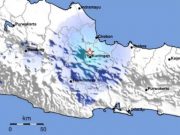Koran Sulindo – Indonesia seperti keranjingan utang. Kebangkrutan di ambang pintu?
TAHUN lalu, tepatnya 30 Juni 2015, Yunani resmi menjadi negara yang menyandang status bangkrut. Karena, negara itu tak mampu membayar utang sebesar US$ 1,7 miliar atau setara Rp 22,7 triliun ke Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund, IMF).
Sebelumnya, tahun 2001 lampau, Argentina juga pernah menjadi negara bangkrut. Utangnya ketika itu mencapai US$ 82 miliar atau sekitar Rp 1.095 triliun. Selain Yunani dan Argentina, masih ada beberapa negara lagi yang mengalami kebangkrutan gara-gara terbenam dalam utang, antara lain Rusia, Jamaika, dan Ekuador. Akankah Indonesia akan bernasib seperti itu, mengingat utang luar negeri Indonesia sampai akhir kuartal II 2016 tercatat sebesar US$ 323,8 miliar atau Rp 4.273 triliun (dengan estimasi kurs Rp 13.197 per US$ 1), dengan debt service ratio sebesar 36,8%?
Kemungkinan buruk itu tetap ada. Apalagi, Indonesia sudah sejak lama seperti keranjingan utang. Bahkan, pemerintah kolonial Belanda ketika hengkang dari Bumi Pertiwi pada tahun 1949 pun mewarisi utang, yang merupakan hasil kesepakatan dari Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda.Sebagai eks penjajah, Belanda mau mengakui kedaulatan Indonesia sebagai negara merdeka antara lain meminta syarat pengalihan utang mereka.
Namun, Presiden Soekarno menolak syarat itu. Akhirnya, utang pemerintah Hindia Belanda tak seluruhnya dialihkan ke Indonesia.
Pada masa pemerintahan Soekarno, Indonesia juga mencari pinjaman luar negeri untuk menggerakkan roda pembangunan di awal kemerdekaan. Bung Karno banyak meminta bantuan dari Uni Soviet dan negara-negara sohibnya. Ada pula utang dari Amerika Serikat, tapi jumlahnya relatif lebih kecil daripada utang ke Uni Soviet dan sekutunya itu.
Ketika pemerintahan berganti, utang luar negeri Indonesia pada tahun 1967 sekitar US$ 2,3 miliar. Pada masa rezim Orde Baru inilah Indonesia mulai seperti orang yang meminum air laut ketika berutang: selalu merasa haus dan ingin minum lagi, ingin minum lagi. Bahkan, warisan utang Hindia Belanda yang ditolak Bung Karno juga dijadwal ulang sebagai utang Indonesia, agar Indonesia mendapat utang baru. Tapi, tidak seperti Bung Karno, Presiden Soeharto lebih memilih berutang ke negara-negara kapitalis Blok Barat dan lembaga-lembaga bentukannya, seperti Bank Dunia, IMF, dan Intergovernmental Group on Indonesia (IGGI). Lembaga yang yang disebutkan belakangan itu adalah sebuah kelompok internasional yang didirikan pada tahun 1967, diprakarsai oleh Amerika Serikat, untuk memberikan utang multilateral kepada Indonesia.
Selama 32 tahun Orde Baru berkuasa, pemerintah Indonesia memiliki utang luar negeri sebesarUS$ 53 miliar plus utang dalam negeri dari Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, sehingga totalnya US$ 171 miliar. Jumlah itulah yang diwariskan ke pemerintah selanjutnya, yang dipimpin Presiden Habibie.
Namun, pemerintahan Presiden Habibie yang hanya sebentar juga gesit mencari utang. Dalam masa pemerintahannya yang pendek, Habibie menambah utang negara ini sebesar US$ 20 miliar. Pemerintahan Habibie meninggalkan warisan utang sekitar US$ 178 miliar ke Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.
Di era Gus Dur, utang luar negeri pemerintah memang berhasil diturunkan, dari US$ 178 miliar menjadi US$ 157 miliar. Tapi, sebenarnya, utang pemerintah secara keseluruhan meningkat. Ketika Gus Dur dipaksa turun sebagai presiden, Megawati Soekarnoputri sebagai penggantinya ketiban utang sebesar Rp 1.273,18 triliun.
Ketika Megawati menjadi presiden, utang luar negeri Indonesia berhasil diturunkan menjadi Rp 1.225,15 triliun pada tahun 2002 dan meningkat sedikit di masa akhir jabatannya pada tahun 2004, menjadi Rp 1.299 triliun. Tapi, ketika Megawati digantikan Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2004, pemerintah yang baru kembali membuat utang luar negeri Indonesia bertambah.
Dalam lima tahun pertama kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden, utang Indonesia menggelembung menjadi Rp 1.700 triliun. Namun, Bank Indonesia pada tahun 2006 berhasil melunasi utang-utang Indonesiake IMF jauh sebelum jatuh tempo.
Lima tahun kedua pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, utang Indonesia terus membengkak. Ketika dia meninggalkan jabatannya, utang luar negeri Indonesia telah mencapai US$ 291 miliar. Jadi, selama 10 tahun berkuasa, Susilo Bambang Yudhoyono berhasil meningkatkan utang luar negeri Indonesia sebesar US$ 150 miliar atau rata-rata US$ 15 miliar per tahun.
“Prestasi” itu ternyata ditingkatkan pada masa sekarang, di era Presiden Joko Widodo. Belum lagi dua tahun menjadi presiden, utang Indonesia sampai kuartal kedua 2016 sudah bertambah hampir US$ 33 miliar.
Padahal, dalam bundel visi-misi yang diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum pada masa kampanye calon presiden dan wakil presiden, pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla mengatakanakan melakukan pengurangan utang negara secara bertahap sehingga rasio utang terhadap produk domestik bruto mengecil. Bahkan, Tjahjo Kumolo yang ketika itu masih Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan—partai pendukung utama Joko Widodo—menyatakanpasangan tersebut secara tegas akan menolak penambahan utang luar negeri baru jika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden untuk periode 2014-2019.
“Kita mau mandiri, sehingga segala bentuk proses pembangunan pendidikan, infrastruktur, harus menggunakan dana sendiri. Menolak bentuk utang baru supaya bisa mengurangi beban utang setiap tahun,” kata Tjahjo, 3 Juni 2014 silam.
Namun, Presiden Joko Widodo sendiri setelah menjadi presiden mengatakan akan menambah utang luar negeri untuk membangun infrastruktur dalam negeri. Tambahan utang tersebut, katanya, tidak akan membebani negara. “Sudah kita hitung keuntungan dan manfaat untuk pendanaan ini jauh dari bunga pinjaman dan ongkos pendanaan,” ujarnya di acara silaturahmi dengan kalangan dunia usaha, 9 Juni 2015 lampau.
Lebih lanjut dikatakan, utang dari luar negeri tersebut bukan untuk konsumsi masyarakat, melainkan untuk pembangunan negara.”Pendanaan ini untuk investasi meningkatkan produktivitas, bukan utang untuk konsumtif, bukan untuk subsidi BBM,” tuturnya.
Joko Widodo juga kerap mengatakan akan melakukan pembangunan berbagai jenis infrastruktur. Pembangunan infrastruktur itu dimaksudkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena akan meningkatkan belanja modal pemerintah. Padahal, dari sisi anggaran, belanja modal sangat bergantung pada kinerja penerimaan, terutama penerimaan perpajakan. Dan, itu masalahnya! Penerimaan pajak jauh di bawah target. Bahkan, diprediksi, program pengampunan pajak yang dijalankan pemerintah juga tak akan mampu menggenjot penerimaan pajak seperti yang ditargetkan.
Apalagi, belanja modal pemerintah pada kuartai pertama 2016 saja berada di level 5,1% dari target senilai Rp201,6 triliun, sehingga ekonomi Indonesia pun tumbuh melambat. Hampir bisa dipastikan, belanja modal akan merosot seiring pemotongan APBN 2016, sebagai upaya menghindari defisit anggaran. Dan itu artinya ekonomi Indonesia bisa saja stagnan atau malah anjlok.Hiks! [Purwadi Sadim]