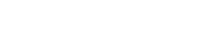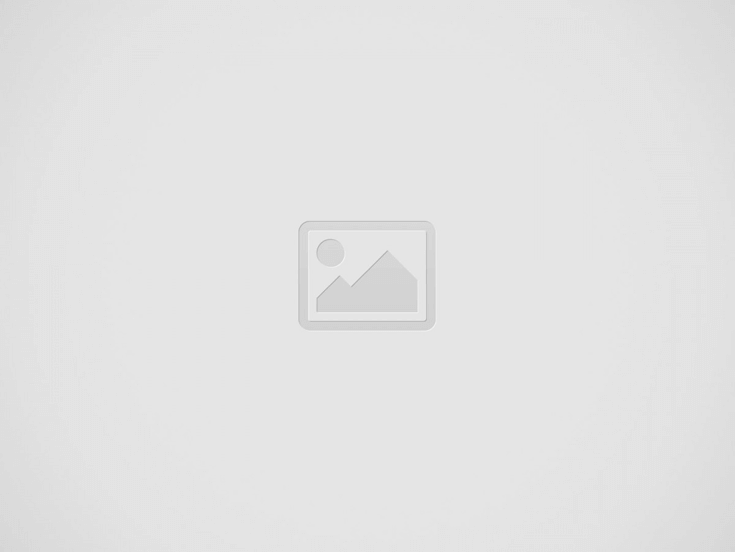Koran Sulindo – Diterbitkan di De Express tanggal 19 Juli 1913, Als ik een Nederlander was atau ‘Seandainya saya seorang Belanda’ adalah esai politik paling kontroversial yang ditulis hingga saat itu oleh seorang Indonesia.
Dalam tulisan itu, Soewardi Soeryaningrat ‘mempertahankan’ pembenaran moral atas permintaan pemerintah kolonial agar orang-orang pribumi menyumbang untuk membiayai pesta peringatan kemerdekaan Belanda atas penjajahan Prancis.
Ironis, karena saat yang sama Belanda justru tengah mempebudak penduduk di Hindia.
Soewardi menulis, seandainya dirinya orang Belanda ia tak bakal menyelenggarakan pesta kemerdekaan di negeri yang justru sedang dirampas kemerdekaannya.
“Sejajar dengan jalan pikiran itu, bukan saja tidak adil, tetapi juga tidak pantas untuk menyuruh orang-orang pribumi memberikan sumbangan uang untuk peringatan itu,” tulis Soewardi dalam artikel itu.
Lebih lanjut Soewardi membeberkan bahwa pemikiran mempersiapkan kemerdekaan saja sudah cukup menghina apalagi ditambah mengeruk isi kantongnya. Baginya itu adalah penghinaan moral dan material sekaligus.
“Tepatnya, apakah akan ada keuntungan Hindia dari peringatan itu jika peringatan harus dilakukan di negeri jajahan ini. Atau apakah kita ingin menyombongkan kekuatan dalam arti politik? Terutama dalam masa-masa ini ketika rakyat Hindia baru saja mengorganisasikan diri mereka yang masih setengah lelap,” tulis Soewardi.
Soewardi mengkritik secara taktis tidak tepat memberikan suatu contoh bagaimana mereka seharusnya memperingati kemerdekaan. Karena hal itu membuat harapan-harapan pribumi didorong dan secara tidak sadar pemerintah turut membangunkan keinginan dan aspirasi mereka. Ya, aspirasi demi terwujudnya kemerdekaan di masa mendatang.
Dengan menulis seolah-olah sebagai orang Belanda, Soewardi memperingatkan koleganya sesama kolonialis tentang bahayanya melakukan peringatan kemerdekaan di negeri yang justru sedang mereka jajah. Pada saat orang-orang pribumi justru mulai memiliki keberanian dan berhenti patuh pada Belanda.
Sifat kontroversial tulisan itu tak semata-mata karena nada provokatifnya semata. Terlebih karena implikasi-implikasi politiknya yang meluas setelah artikel tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dan kemudian dibagi-bagi sebagai selebaran terpisah.
Inilah kali pertama suatu kritik terhadap pemerintah Hindia Belanda ditulis oleh seorang cendekiawan Indonesia sekaligus dibaca kalangan luas di luar golongan cendekiawan semata.
Soewardi Soeryaningrat lahir pada tanggal 2 Mei 1889 dari keluarga aristokratis terkenal di Yogyakarta, Paku Alam. Ayahnya adalah Pangeran Soeryaningrat, putra tertua Paku Alam III dari istri permaisuri.
Soeryaningrat urung mewarisi tahta Paku Alam, karena saat Paku Alam III meninggal, Belanda memberikan tahta diberikan saudara sepupu Paku Alam III yang kemudian bergelar Paku Alam IV dan digantikan lagi oleh adik Paku Alam III sebagai Paku Alam V.
Soeryaningrat relatif jatuh ‘miskin’ karena pengalihan tahta itu membuat pengurangan segala bantuan pemerintah Belanda kepada Soeryaningrat. Ia hanya menjadi satu dari sekian banyak pangeran dalam rombongan pangeran-pangeran di keluarga Paku Alam.
Latar belakang itulah yang membuat Soeryaningrat mendorong anak-anaknya mengejar karir profesional sekaligus tampil sebagai pembaruan di lingkungan mereka. Sementara kakaknya Soerjopranoto belajar sekolah pertanian di Bogor, Soewardi justru berangkat ke Stovia untuk menjadi dokter.
Keadaan ekonomi dan status sosial Soeryaningrat menjelaskan mengapa baik Soewardi maupun Soerjopranoto tidak menerima pendidikan istimewa untuk golongan elite pribumi seperti HBS maupun OSVIA.
Namun di sisi lain, dari dari keluarga aristokrat Pakualam yang merupakan golongan elit struktur sosial masyarakat Jawa, pandangan dan sikap politik Soewardi memberikan pengaruh yang besar bagi golongan penguasa Jawa yang kala itu kesadaran sosialnya masih lelap belum dibangunkan.
Kedudukan itu menjelaskan mengapa kritiknya mempunyai kekuatan yang lebih berbahaya sebagai pembentuk pendapat yang dianggap sanggup mengancam pemerintah Belanda. Lebih berbahaya dibanding Tjipto Mangoenkoesoema, Abdoel Moeis, atau Wignyadisastra.
Meski mereka bertiga adalah pengecam-pengecam kolonial yang kuat, mereka tetaplah ‘pendatang’ baru yang datang dari latar belakang sosial yang belum mapan. Termasuk dalam hal ini adalah Doewes Dekker yang Indo. Ia tetap dianggap oleh orang-orang Jawa sebagai golongan orang yang berada di luar masyarakat mereka.
Latar belakang keluarga Soewardi menjadi penjelasan dari sifat-sifat dasar kegemparan Als ik een Nederlander was dalam tulisan itu.
Takashi Shiraishi dalam Zaman Bergerak Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926 menyebut walau tulisannya amat radikal, sejatinya artikel itu tak berbeda dengan artikel-artikel lain yang dimuat De Express yang hanya dibaca segelintir mereka yang mengerti bahasa itu.
Begitu tulisan Soewardi diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, segera saja esai politik Soewardi itu menjangkau pembaca yang lebih luas.
Pemerintah kolonial langsung melihat penerjemahan itu sebagai bahaya karena Soewardi sanggup menunjukkan dirinya menjadi ‘penghubung’ yang baik dengan masyarakatnya sekaligus mengusung gagasan Douwes Dekker yang subversif kepada bumiputra. Inilah alasan utama pemerintah mengambil tindakan tegas dengan membuang Soewardi, Tjipto dan Douwes Dekker dari Hindia.
Tak Terbayangkan
Takashi menyebut, gagasan Als ik een Nederlander was bukan hanya tak terbayangkan dan memang tidak mungkin bagi bumiputra untuk menjadi orang Belanda sungguhan. Selain itu gagasan Als ik een Nederlander was tak mungkin diungkap secara terbuka, sekalipun ide tersebut ada di kepala hampir semua penduduk pribumi.
Dengan mengungkapkan apa yang tidak mungkin diungkapkan, Soewardi mentransformasikan bahasa Belanda dan dengan terjemahan bahasa Melayu, ke dalam bahasa ngokonya menempatkan tata kolonial dalam perubahan.
Jika Soewardi bisa dengan enteng mengatakan ‘Seandainya saya seorang Belanda’ dengan mudah orang lain juga bisa meniru dengan kalimat, “Seandainya saya seorang menteri jajahan. Seandainya saya seorang residen atau Seandainya saya seorang bupati atau kalimat lain seperti seandainya saya seorang kuli.”
Soewardi sendiri, dalam suratnya berjudul Peringatan Kemerdekaan dan Perampasan Kemerdekaan menulis, ia telah diberitahu oleh pejabat Pengadilan Belanda bahwa alasan pembuangannya oleh pemerintah kolonial adalah terjemahan artikel Als ik een Nederlander was.
Sebenarnya, baik Soewardi, Tjipto maupun Douwes Dekker telah berkali-kali melancarkan kritik keras terhadap pemerintah dalam banyak tulisannya, namun hanya sekaranglah pemerintah benar-benar mulai menganggap kritik itu sebagai ancaman berat pada kemantapan tata kolonial.
Sebelumnya, meski menulis kritik sangat keras mereka hanya memberikan pengaruh yang terbatas, paling banter hanya di kalangan cendekiawan berpendidikan barat yang umumnya tak mempunyai hubungan dengan massa rakyat.
Tulisan mereka, walau provokatif dianggap tak lebih dari kepandaian ‘berbicara’ dalam menyampaikan gagasan-gagasan ketimbang aksi pengerahan massa rakyat untuk tindakan militan.
Tetapi dengan menggunakan peringatan 100 tahun kemerdekaan Belanda sebagai fokus untuk menarik dukungan di tengah-tengah massa rakyat, dan penerjemahan artikel itu ke dalam bahasa Melayu dianggap Belanda sebagai upaya mereka untuk memastikan pendukung yang lebih luas.
Belanda sadar betul kekuatan eksplosif Komite Bumiputra jika komite ini dibiarkan meneruskan keberadaannya untuk terus-menerus melakukan tindakan politik melawan pemerintah. Inilah yang memang membuat Soewardi, Tjipto dan Douwes Dekker ditahan dan diinterogasi.
Pengaruh Tjipto
Hal paling menarik adalah bahwa Mr Mosanto, petugas Belanda yang menginterogasi mereka tak percaya bahwa artikel Als ik een Nederlander was adalah benar-benar tulisan Soewardi. Ia bahkan mendesak Soewardi agar memberitahukan nama penulis sebenarnya.
Baik Mosanto atau pemerintah Hindia Belanda mengira artikel itu adalah tulisan Tjipto, atau setidak-tidaknya ditulis Soewardi di bawah tekanan dan pengaruh Tjipto.
Seminggu setelah Als ik een Nederlander was, pada tanggal 28 Juli 1913, Soewardi dalam De Express menulis sebuah artikel berjudul, ‘Semua untuk Satu juga Satu untuk Semua’.
Artikel itu mengecam tindakan pemerintah yang terus menerus mengganggu Komite Bumiputra sekaligus membuat pernyataab bahwa artikel Als ik een Nederlander was adalah “ditulisannya sendiri.”
Di sisi lain, sepanjang penahanan dan interogasi Tjipto tak pernah membantah atau membenarkan tuduhan bahwa dialah penulis artikel itu.
Hal menarik yang lain adalah reaksi golongan penguasa Jawa terhadap keputusan pemerintah mengirim Soewardi bersama-sama dengan Tjipto dan Douwes Dekker ke pembuangan akibat kegiatan mereka di Komite Bumiputra.
Dwijosewoyo dan dr Wahidin termasuk beberapa anggota-anggota terkemuka Boedi Oetomo segera membentuk sebuah panitia khusus dengan maksud mengirim utusan kepada pemerintah untuk memintakan pengampunan kepada Soewardi. Panitia itu juga didukung penuh oleh Tjokroaminoto dan sahabat-sahabatnya di Sarekat Islam.
Selama pertemuan dengan DA Rinkes penasihat pemerintah untuk urusan Bumiputra, Dwijosewoyo menyebut dirinya secara pribadi telah kehilangan harapan untuk membatasi pendapat dan tindakan-tindakan Tjipto tentang pemerintah.
Akan tetapi karena kenal baik dengan Soewardi dan keluarga-keluarganya, Dwijosewoyo berani memberikan jaminan bahwa Soewardi berwatak baik dan dapat dibujuk di masa-masa mendatang agar menahan diri dalam mengungkapkan pendapat-pendapatnya yang radikal. Karena alasan inilah, Dwijosewoyo memohon agar Pemerintah bersikap sedikit lebih lunak kepada Soewardi.
Sebenarnya, semula pemerintah tak percaya bahwa Soewardi penulis Als ik een Nederlander was itu. Tapi begitu Soeward membuat pernyataan bahwa dialah satu-satunya yang bertanggung jawab atas tulisan itu, Pemerintah menuntut Soewardi sama Tjipto dan Douwes Dekker yang juga sedang ditahan akibat sikap politik mereka.
Lebih Berbahaya
Pengakuan itu dianggap sebagai ancaman yang lebih besar terhadap kemantapan tata pemerintahan kolonial di Hindia karena kritik disampaikan oleh mereka yang dianggap memiliki legitimasi sosial.
Pemerintah menganggap, pendapat Soewardi memiliki nilai lebih berbahaya dan gawat untuk menciptakan pendirian rakyat dibanding pendapat perorangan-perorangan di Komite Bumiputra. Bagi Pemerintah, karena status sosialnya Soewardi justru harus mendapat hukuman yang lebih keras dibanding yang lain.
Pendapat itu jelas berbeda dengan pemikiran di kalangan penguasa Jawa. Bagi mereka, latar belakang aristokratis Soewardi seharusnya memberikan hak untuk menerima perlakuan istimewa dari pemerintah.
Tidak masuk akal bagi priyayi Jawa di tahun 1913 bahwa seorang pangeran dari rumah Paku Alam dihukum seolah-olah ia penjahat politik biasa dari keluarga yang tak jelas dan integritasnya meragukan sebagaimana para priyayi-priyayi itu memandang Tjipto.
Tanpa perlu menghayati dan memahami pesan radikal yang tekandung dalam Als ik een Nederlander was, para priyayi-priyayi itu melihat radikalisme Soewardi dalam makna yang berbeda dengan ‘pesan-pesan’ yang mereka baca dari tulisan Tjipto.
Meski artikel Als ik een Nederlander was itu terbukti gagal merangsang dukungan penguasa Jawa, artikel itu tetap merupakan tulisan paling berkesan, provokatif dan radikal yang pernah ditulis pada waktu itu oleh orang Indonesia.
Pandangan-pandangan yang diungkapkan di dalamnya mendahului setiap gagasan yang dikemukakan oleh cendekiawan-cendekiawan Jawa yang paling sadar politik. Bagi Belanda, artikel itu berbahaya karena menanamkan kesadaran bahwa orang-orang Indonesia masih berada di bawah dominasi asing.
Di mata orang pribumi, Soewardi dianggap menampilkan diri sebagai satria sejati, seorang satria mirip Bima dalam dunia pewayangan yang berbicara ngoko dan apa adanya kepada semua orang bahkan termasuk para dewa. Pembuangannya ke negeri Belanda justru makin menegaskan mandatnya sebagai satria sejati karena dianggap sebagai pengorbanannya kepada bangsa.
Meski begitu, gagasan Soewardi tetap tak pernah dominan karena ‘satria’ tanpa perlindungan Pemerintah dianggap terlalu subversif bagi kaum muda dan jauh dari kesadaran mereka. Suara Soewardi kalah dominan dibanding Tjokroaminoto dengan SI-nya.
Tindakan Pemerintah membuang Tjipto, Soewardi dan Douwes Dekker menjadi bukti betapa berbahayanya pikiran mereka bagi tata kolonial. [TGU]
* Tulisan ini pertama dimuat 17 Juli 2018