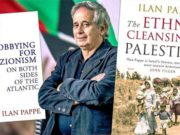Catatan Cak AT:
Ada sebuah dongeng tua tentang seekor keledai yang mati kelaparan karena tidak bisa memutuskan akan memakan jerami di kiri atau di kanan. Cerita ini, meskipun konyol, seringkali teringat ketika kita berbicara tentang “disunity” atau perpecahan umat Islam.
Betapa mudahnya umat Islam di seluruh dunia terjebak dalam narasi yang sama: “Kita ini tidak bersatu!” Seruan yang dramatis, penuh air mata, tapi kadang lebih mirip drama telenovela daripada refleksi yang benar-benar kritis.
Namun, mari kita bongkar mitos ini dengan cara yang lebih santai, sambil tetap serius. Benarkah umat Islam sedemikian terpecah seperti klaim banyak pihak?
Shaykh M. A. Kholwadia dalam opininya di Al Jazeera mengajak kita untuk membuka mata (dan mungkin juga sedikit kepala) bahwa persatuan umat sebenarnya sudah ada —meski tidak dalam bentuk pan-Islamisme utopis ala Kekhalifahan Ottoman.
Kita sering mendengar orang berkata, “Kita harus bersatu!” Tapi, apa yang sebenarnya mereka maksud? Sebagian mungkin membayangkan peta dunia dengan garis-garis perbatasan yang hilang, semua wilayah Muslim bersatu di bawah satu bendera. Romantis? Mungkin. Realistis? Hampir tidak.
Faktanya, persatuan umat Islam sudah nyata dalam hal yang sering kita abaikan. Ritual shalat lima waktu, puasa Ramadan, hingga tradisi kurban di Idul Adha menunjukkan persamaan yang melampaui batas politik, budaya, dan bahkan bahasa. Tapi, ya, itu tidak keren di media sosial.
Siapa yang mau memposting foto jamaah shalat subuh dengan caption, “Lihat betapa kita semua kompak berjamaah?” Itu tidak instagramable.
Shaykh Kholwadia mengingatkan bahwa narasi “disunity” ini sebenarnya hadiah busuk dari para penjajah kolonial. Bayangkan seseorang datang ke rumah Anda, merampas tanah, lalu berkata, “Kalian sekeluarga tidak kompak, sih, makanya tanah kalian mudah diambil.”
Ironis, bukan? Begitu pula nasib umat Islam. Perbatasan-perbatasan artifisial yang dibuat oleh penjajah masih menjadi sumber konflik hari ini. Namun, mari kita tepuk tangan untuk fakta bahwa meski dirajam dengan propaganda selama ratusan tahun, umat Islam tetap mempertahankan tradisi yang sama.
Perjalanan haji, doa-doa yang diucapkan dengan bahasa Arab yang sama, dan solidaritas untuk Palestina, itu semua bukti bahwa persatuan kita ada—meski mungkin tidak seperti yang diimpikan para penggemar serial sejarah Kekhalifahan Ottoman.
Salah satu kesalahan terbesar kita adalah menganggap perbedaan dan keragaman sebagai sumber masalah. Padahal, sebagaimana ditegaskan Shaykh Kholwadia, sejak awal Islam itu inklusif.
Perbedaan pendapat dalam mazhab? Itu bukan tanda perpecahan, melainkan kekayaan intelektual. Namun, mari kita jujur: kadang perbedaan ini jadi alasan debat kusir.
Sebagai contoh, ketika kita sibuk bertengkar soal posisi tangan saat shalat —di dada atau di bawah pusar— mungkin musuh-musuh kita sedang tertawa sambil berkata, “Lihat, mereka ribut soal tangan!” Selama ratusan tahun kita bertengkar soal qunut, apa hasilnya?
Shaykh Kholwadia memberi contoh inspiratif tentang bagaimana para ulama Deoband di India bangkit dari kekalahan setelah Pemberontakan 1857 melawan Inggris. Bukannya menangis sambil menyalahkan “disunity”, mereka memilih untuk bangkit.
Hasilnya? Lembaga pendidikan seperti Darul Uloom Deoband menjadi mercusuar ilmu pengetahuan Islam di anak benua India.
Kita, umat Islam hari ini, perlu belajar dari mereka. Daripada terjebak dalam ratapan tanpa solusi, kita harus fokus pada apa yang bisa kita bangun bersama, dari pendidikan hingga ekonomi, dari teknologi hingga solidaritas sosial.
Jadi, mari kita berhenti menjadi “keledai yang lapar.” Kita punya lebih dari cukup alasan untuk percaya bahwa umat Islam sebenarnya lebih bersatu dari yang kita pikirkan. Perbedaan bukanlah musuh, tapi rahmat, dan kita tidak perlu bendera pan-Islamisme untuk menunjukkan kekuatan kita.
Sebagai umat yang percaya pada kebesaran Allah, mungkin saatnya kita menggeser fokus dari ratapan ke tindakan. Karena, seperti yang diingatkan Shaykh Kholwadia, persatuan bukan soal seragam, tapi soal keberanian untuk bergerak maju meskipun dalam keragaman. Jadi, apa langkah Anda berikutnya?
Cak AT – Ahmadie Thaha | Kolumnis