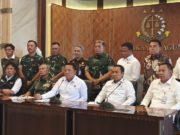Semula agak ragu ikut terbang. Tapi setelah Ketua Paralayang Indonesia Wahyu Yudha Dewanto berkata “ini venue dengan tingkat kesulitan tinggi”, ragu pun berganti penasaran.
Venue yang dimaksud Wahyu adalah Bukit Gracia di Kampung Buton, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Itulah arena lomba untuk cabang olah raga paralayang PON Papua 2021 yang sudah menyelesaikan lomba sejak beberapa hari lalu.
Mengapa bertingkat kesulitan tinggi? Karena selain berketinggian 370 meter yang adalah tertinggi dibanding tempat-tempat lain termasuk Puncak di Bogor dan Bali, juga karena medan dan kecepatan anginnya yang menantang.
Sudah begitu, Bukit Gracia menawarkan panorama yang memanjakan mata. Sebelum terbang pun, panorama demikian sudah terasa manakala menaiki bukit tersebut.
Berada di puncaknya yang menjadi tempat tinggal landas paralayang, terlihatlah pemandangan indah kota Jayapura, Teluk Yos Sudarso dan Teluk Youtefa. Selain itu, tentu saja tampak Jembatan Merah yang ikonik.
Tapi begitu, melihat hamparan karpet yang menutupi tanah berkapur berkemiringan 30 derajat, nyali menciut lagi. “Santai saja pak,” kata Reza Tampenawas, atlet paralayang Sulawesi Utara yang menjadi tandem master Antara.
Reza sudah mengenal paralayang sejak tamat SMA di Manado pada 2016. Kini berusia 22 tahun, beberapa hari lalu Reza meraih medali perunggu paralayang PON Papua setelah finis urutan ketiga nomor ketepatan mendarat.
Dia dan Wahyu adalah jago-jago ketepatan mendarat. Bedanya, Wahyu yang mantan juara dunia, sudah tak aktif berkompetisi, sedangkan Reza baru mengawali karir profesionalnya.
Reza memasangkan seat harness atau tempat duduk saat terbang, ke tubuh Antara, untuk kemudian ditalikan ke harness-nya sendiri. Lalu dia menyambungkannyah ke tali parasut yang menurut Wahyu harganya Rp 100 juta per unit.
Parasut, seat harness, dan helm adalah alat utama paralayang. Masih ada perlengkapan lain seperti variometer, radio/HT, GPS, wind meter, dan peta lokasi terbang, sebagai cadangan. Untuk terbang tandem, tentu saja seat harness-nya harus dua. Satu untuk si tamu, satu untuk si tandem master.
Hati pun plong
“Kita berdoa dulu,” ajak Reza, yang setengah menit kemudian disusul satu instruksi. “Begitu saya kata lari, lari ya pak, jangan berhenti.”
Omongan Reza malah membuat Antara makin gelisah. Sambil menatap ke bawah, pikiran melayang, “bagaimana kalau kaki malah lebih dulu bergetar sehingga tak bisa berlari?”
“Jangan menatap ke bawah pak,” kata Reza, seolah mengetahui kegelisahan hati.
Seorang ibu berusia sekitar 40-an tahun yang beberapa langkah di sebelah yang juga bersiap hendak terbang tandem, menyimak percakapan kami. “Sudah berapa kali terbang bu?” Antara iseng menyapa si ibu. Bukannya menjawab, dia malah tersenyum, menjawab dengan mengangkat satu jari.
Rupanya, dia pun baru pertama terbang, dan agaknya dia juga diam-diam cemas sampai-sampai malas bersuara. Si ibu adalah satu dari puluhan orang yang pagi itu mencoba terbang berparalayang.
Ada yang terbang sendiri, tapi lebih banyak lagi yang terbang tandem, termasuk Atilla, bocah perempuan kelas dua SD asal Manado, Sulawesi Utara. “Enak,” jawab Atilla saat ditanyai kesannya terbang di ketinggian dalam usia semuda itu.
Kembali ke puncak Bukit Gracia, Reza sudah siap menerbangkan Antara. Seat harness sudah tertambat lekat ke tali parasut, sementara parasut sudah dihamparkan di atas karpet, siap ditarik kami berdua untuk kemudian didorong angin.
Kaki terayun beberapa langkah, parasut mengembang lebih cepat. Angin naik ideal. Sejenak angin mendorong kami ke belakang, lalu ke depan lagi, kemudian pelan-pelan membuat kaki kami terangkat untuk tak lagi menyentuh karpet landasan.
Ternyata, tak perlu berlari seheboh yang dipikirkan. Cukup jalan pelan menuruni medan lepas landas. Dan hanya butuh beberapa langkah, kami pun mengangkasa.
Beberapa detik setelah kaki tak lagi menyentuh tanah, ngeri seketika sirna. Gantinya, hati menjadi plong, diteruskan senang tak terhingga.
Muncul rasa superior terhadap apa pun yang ada di bawah sana. Rasa ini mungkin juga dirasakan burung manakala mengepakkan sayapnya demi mengangkasa menembus awan.
Kaki paling penting
Konsep terbang paralayang sendiri sederhana. Parasut terbuat dari kain nylon berfungsi sebagai sayap seperti pada burung, yang dihubungkan oleh tali-tali sebagai cantolan seat harness. Dalam terbang tandem, seat harness ini ada dua. Satu untuk tandem master, satu untuk tamu.
Begitu ada gerakan saat melintasi udara bebas, kain nylon seharga seratus juta rupiah itu menggembung mencipta tekanan. Ia membentuk sayap untuk kemudian terbang, dalam kecepatan tak lebih dari 50 km/jam.
Agar bisa lepas landas, perlu lereng bukit rata berkemiringan 20-30 derajat seperti di Bukit Gracia ini. Jika lereng tak ada, mesin winch bisa menarik parasut mengembang di lapangan terbuka, hingga terbang.
Yang jelas, paralayang mutlak perlu angin, karena tak akan ada yang bisa terbang kalau tidak ada angin. Untuk itu, sebelum terbang, arah mata angin harus lebih dahulu dipetakan. Jika tekanan anginnya besar, penerbang bisa terbang lebih tinggi yang bahkan bisa mengelilingi beberapa titik. Sebaliknya, jika tekanan angin terlalu kecil, jangan coba-coba terbang.
Anginnya sendiri ada dua jenis. Pertama, angin naik yang menabrak lereng. Kedua, angin naik karena termal atau panas dari bumi. Dengan memanfaatkan kedua sumber angin, penerbang bisa terbang amat tinggi sejauh yang diinginkan. “Inti paralayang itu mencari termal dan mengelola angin,” kata Wahyu.
Begitu melayang di udara, bersama Reza yang piawai mengelola angin dan mencari termal, keindahan pun terhampar sempurna. Sensasinya paripurna.
Tapi sebentar lagi harus mendarat. “Ketika akan mendarat, kaki jangan ditekuk ya, rentangkan saja,” kata Reza, saat babak terakhir terbang berparalayang kian dekat.
Kaki adalah bagian tubuh yang paling instrumental dalam paralayang, baik saat lepas landas maupun mendarat. Saat lepas landas, kaki harus dipakai sebagai penopang, sementara saat mendarat kaki digunakan sebagai rem guna memperlambat laju parasut agar tidak terus terbang.
Layak didukung
Selama hampir 20 menit kami melayang-layang di atas Jayapura. Dua teluk yang bertepikan pantai kota Jayapura tampak eksotis, salah satunya dibelah Jembatan Merah yang ikonik.
Benar kata Wahyu, selain bermedan sulit, Bukit Gracia juga menawarkan keindahan. Saat terbang orang akan melihat empat panorama sekaligus. Pepohonan rimbun di sekitar perbukitan dan gunung, kemudian hamparan rumah dan bangunan, Teluk Youtefa dan Jembatan Merah.
Rangkaian panorama indah ini membuat berparalayang di Bukti Gracia kian mengasyikkan. Tapi di mana-mana paralayang memang mengasyikan. Sudah begitu, memicu adrenalin, sampai banyak orang yang ketagihan.
Tak heran, mengutip kalimat Wahyu, “penggemar paralayang kian banyak dari waktu ke waktu.” Padahal, paralayang itu tidak murah. “Di Puncak, tarifnya Rp 400 ribu untuk terbang selama sepuluh menit. Di Bali bisa sampai Rp 1 juta,” kata Wahyu.
Tetap saja, harga semahal itu tak masalah bagi sebagian orang. Buktinya, di Puncak, setiap hari ada 200 orang yang terbang. Di Bali lebih banyak lagi, 1.000 tamu per hari, sedangkan di Bunaken, 100 tamu per hari.
Manakala masyarakat makin antusiastis seperti itu, talenta-talenta baru tertemukan, lalu mendorong turnamen semakin sering diadakan. Karenanya, atlet seperti Reza Tampenawas tak pernah kekurangan arena guna menempa diri agar siap menggebrak dunia, seperti pernah dilakukan Wahyu.
Wahyu sendiri sudah mengusulkan agar kejuaraan dunia paralayang nomor ketepatan mendarat, digelar di Bukit Gracia, tahun depan. Usul ini layak didukung, apalagi jika dikaitkan dengan keterpakaian venue olahraga setelah PON Papua dan sport-tourism di Jayapura. (Jafar M Sidik/Antara)