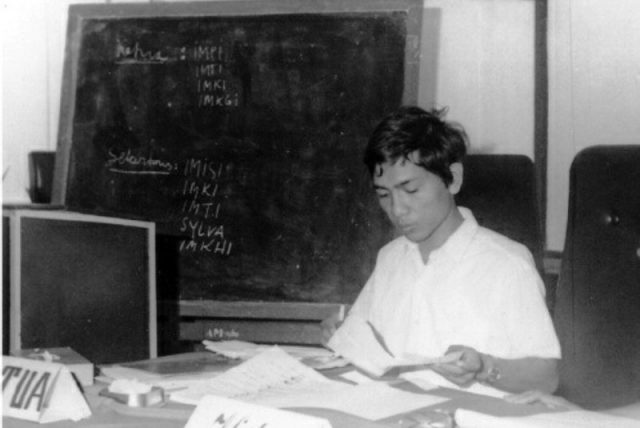Koran Sulindo – Mentari belum lagi menampakkan wajahnya. Subuh itu, Hariman Siregar masih tertidur di selnya di Rumah Tahanan Militer (RTM) Budi Utomo, Jakarta. Itulah hari kedua ia mendekam di salah satu sel di blok 5, salah satu blok yang menyeramkan di RTM Budi Utomo karena berpenghuni orang-orang yang akan dihukum mati.
Tak jauh dari tempat Hariman berbaring terbujur dua sosok rekan satu selnya: yang seorang adalah Mayor Jenderal (Polisi) Soewarno, mantan Panglima Daerah Kepolisian Jakarta saat Peristiwa 30 September 1965, dan seorang lainnya adalah Mayor Jenderal Soeratmo, mantan Komandan Komando Logistik Angkatan Darat (Kologad). Kedua rekan satu sel Hariman itu adalah tahanan politik yang dituduh terlibat Partai Komunis Indonesia (PKI).
Di keheningan subuh itu tiba-tiba pintu sel dibuka. Seorang petugas RTM membangunkan Hariman, dengan membawa sebuah kabar penting: Sriyanti Sarbini Soemawinata, istri Hariman, dalam kondisi mengkhawatirkan di Rumah Sakit St. Carolus, Jakarta. Hariman diminta bergegas untuk menjenguk istrinya ke rumah sakit.
Sepanjang perjalanan menuju rumah sakit, perasaan Hariman waswas. Saat ditinggal Hariman beberapa hari sebelumnya, Yanti memang dalam keadaan hamil tua. Karena itu, Hariman mengkhawatirkan keadaan Yanti dan anak dalam rahimnya.
Setiba di RS St. Carolus, Hariman benar-benar terpukul. Ia mendapati Yanti dalam kondisi kritis, sedangkan anak yang dilahirkan sudah meninggal dunia.
Air mata Hariman mengalir, namun beberapa jenak kemudian Hariman berusaha tegar. Sore hari itu juga, ia ikut mengantar jenazah anaknya ke pemakaman Karet Bivak, Jakarta Pusat.
Setelah itu, Hariman kembali ke rumah sakit untuk menunggui Yanti. Sepanjang malam itu, ia menunggui istri yang sangat dicintainya itu. Tapi, pukul 03.00 dini hari, ia terpaksa harus kembali ke RTM Budi Utomo, sesuai aturan yang berlaku saat itu. Saat Hariman meninggalkan rumah sakit, kondisi Yanti masih dalam keadaan sadar.
Di dalam selnya, Hariman tak bisa memenjamkan mata. Pikiran dan perasaannya masih tertuju kepada istrinya yang terbaring lemah di rumah sakit.
Saat pagi baru datang, petugas RTM kembali membawa Hariman ke rumah sakit. Sampai di sana, ia mendapati sang istri sudah koma. Hariman pun diizinkan menunggui Yanti selama sepuluh hari penuh. “Tapi, kesehatannya tak pulih lagi. Sejak itu, Yanti hilang ingatan,” kenang Hariman.
Setelah izinnya habis, Hariman pun kembali ke RTM Budi Utomo. Sepeninggalnya, yang menunggui Yanti adalah ayahanda Hariman, Kalisati Siregar. Tapi, karena kecapekan dan usia tua, beberapa hari kemudian Kalisati jatuh sakit. Sakit sang ayah ternyata cukup serius. Hariman pun kembali diizinkan ke luar tahanan, untuk menunggui ayahnya di rumah sakit.
Cobaan Tuhan masih mendera Hariman. Pada 29 September 1974, di malam hari, Kalisati Siregar mengembuskan napasnya yang terakhir. “Keesokan harinya, Ayah dimakamkan. Kota Jakarta kala itu sedang dipenuhi kibaran bendera setengah tiang. Tentu saja orang-orang memasang bendera setengah tiang bukan untuk menghormati Ayah, tapi karena tepat 30 September bendera memang dikibarkan setengah tiang, untuk memperingati Peristiwa G30S. Namun, itu semua saya anggap saja untuk menghormati mendiang Ayah,” kenang Hariman.
Mendekam di penjara, kehilangan bayi kembar, sang istri yang hilang ingatan, wafatnya ayahanda, serta mertua–Profesor Sarbini Sumawinata—yang juga mendekam di penjara. Itulah garis tangan Hariman. Sebagai manusia biasa, rentetan peristiwa menyedihkan tersebut sempat mengguncang jiwanya. Ia bisa dikatakan telah mencapai dasar kepedihan yang bisa dialami seorang anak manusia.
Tak syak lag, itulah masa mahaduka dalam hidupnya. Dalam percakapan dengan siapa pun, jarang Hariman menyinggung masa-masa ini. Kalaupun ia mengisahkannya, selalu dengan mata berkaca, pertanda ia tak mampu menahan kesedihan bila mengenang masa-masa tersebut.
Sungguhpun begitu, Hariman menyadari benar, itulah konsekuensi yang harus ia tanggung atas sikap kritisnya terhadap rezim Orde Baru. Semua kesedihan itu merupakan harga yang harus ia bayar karena melawan rezim otoriter dan represif. Sebagai ekspresi kesedihan itu, Hariman selama di penjara selalu membuat catatan harian atau jurnal.
“Tapi, bila membaca kembali catatan harian itu, yang terasa hanya kecengengan belaka—sekadar uraian perasaan dan pemikiran yang mendatangkan kesedihan. Padahal, gue enggak boleh lengah, apalagi kalah, oleh kesedihan. Gue harus mampu membuat diri gue sendiri menjadi kuat. Gue sedang melawan kekuasaan Soeharto, sampai mati gue enggak boleh kalah. Kita mesti kuat, meskipun dia [Soeharto] terus menginjak-nginjak kita,” begitulah tekad Hariman. Ia memang bertekad tak mau kalah dalam menghadapi rezim Soeharto, meski badannya mendekam di penjara.
Hariman mengenang masa-masa mendekam di penjara: “Di penjara sebenarnya sedang berhadapan juga dengan kekuasaan Soeharto dalam wujudnya yang lain. Di penjara, kekuasaan itu dimanifestasikan melalui sipir penjara, prajurit penjaga, petugas pengawal, bahkan lewat benda mati seperti tembok dan gembok! Kalau kita sudah dikunci di dalam sel, kita tak bisa melawan kekuasaan tembok dan gembok. Kita tak bisa lagi melawan prajurit dan penjaga penjara yang mengunci sel.
Wujud kekuasaan kini berganti. Tidak lagi berupa sosok Soeharto, melainkan bunyi ‘klik’ misterius ketika pintu sel kita digembok dari luar. Dan suara ‘klik’ itu sungguh menimbulkan rasa kebencian yang amat sangat. “Karena, kita secara telak menyadari kita sangat tidak berdaya. Tidak memiliki kekuatan perlawanan apa pun, kecuali kepasrahan,” tuturnya.
Apa yang dialami Hariman merupakan imbas dari Peristiwa 15 Januari 1974 atau yang lebih dikenal dengan sebutan Peristiwa Malari—sebuah aksi kritis mahasiswa terhadap modal asing, yang berbuntut kerusuhan sosial di Jakarta. Sebelumnya, ia tak pernah membayangkan hidupnya akan memasuki ruangan sekelam itu.
Sampai hari ini, luka tersebut mungkin masih membekas kuat dalam jiwa Hariman Siregar. Namun, luka itu pula yang terus menggelorakan semangat perlawanan kaum muda Indonesia terhadap kelancungan para penguasa. [COK]